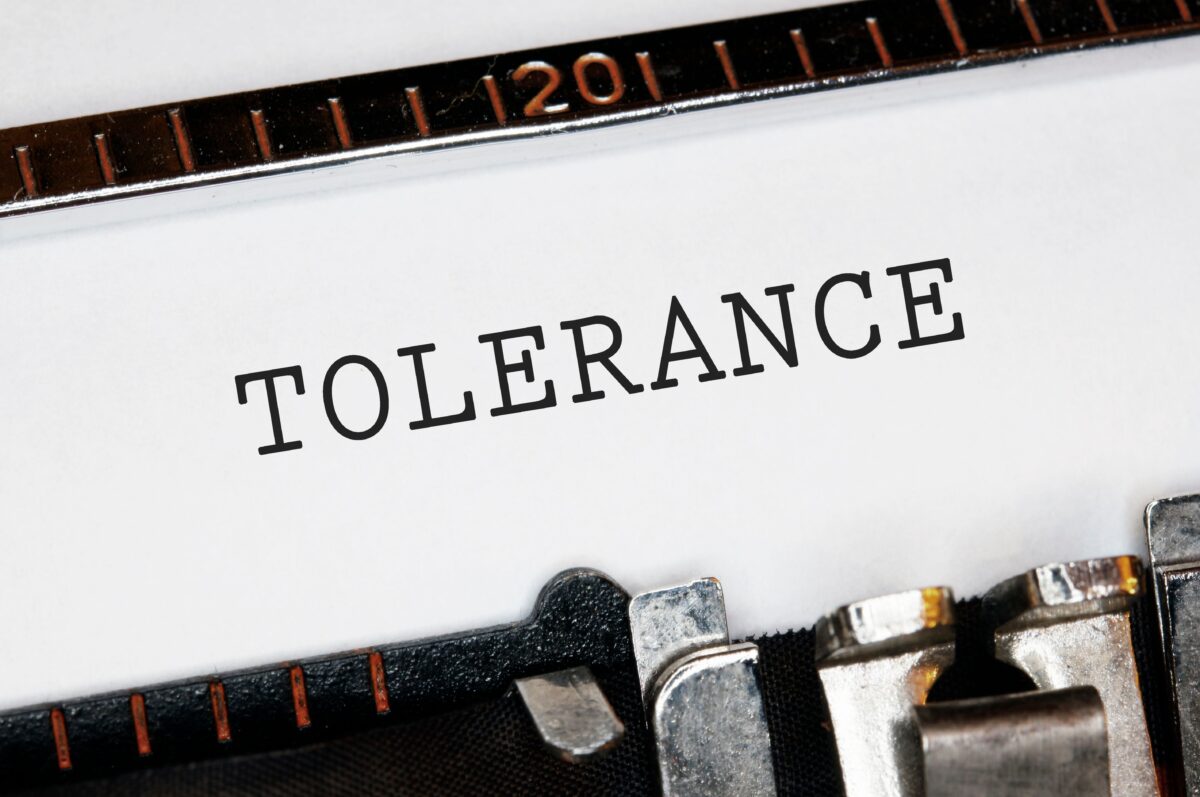- Deretan peristiwa intoleransi menjadi sinyal memburuknya perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
- Klientelistime antara elite politik lokal dan rakyat memperparah intoleransi di tengah menguatnya otoritarianisme.
- Cara pandang moderasi agama yang masih didominasi kontrol negara gagal menyelesaikan persoalan intoleransi.
Tepat sebulan setelah terjadinya peristiwa perusakan rumah singgah dan pembubaran acara retret di Cidahu, Jawa Barat pada 27 Juni lalu, insiden serupa kembali terjadi. Kali ini di Padang, Sumatra Barat, pada 27 Juli, terjadi perusakan rumah doa umat Kristen.
Rentetan peristiwa intoleransi ini menjadi pertanda yang mengindikasikan semakin buruknya perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, terutama dalam hal kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan.
Sejak Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai presiden pada Oktober 2024, telah terjadi sejumlah peristiwa ancaman terhadap kelompok agama dan/atau pemeluk keyakinan minoritas dalam menjalankan praktik keagamaan dan kepercayaan mereka.
Selain kekerasan terhadap komunitas antaragama, kekerasan juga dialami oleh komunitas intra-agama, seperti yang dialami oleh Jamaah Ahmadiyyah Indonesia yang mendapat ancaman saat hendak mengadakan acara Jalsah Salanah pada akhir tahun lalu.
Dalam Asta Cita-nya, Prabowo berjanji akan “meningkatan toleransi antarumat beragama” sebagai salah satu visi utama dalam pemerintahannya. Namun, pemerintah justru menunjukkan sikap yang bertolak belakang saat merespons masalah intoleransi.
Alih-alih membela korban, Staf Khusus Menteri HAM malah menyatakan dirinya siap menjadi penjamin penangguhan penahanan bagi para tersangka dalam kasus Cidahu.
Lantas, apa yang membuat praktik-praktik intoleran tetap tumbuh subur di tengah rezim yang kian otoriter ini?
Politikus Demokratis, Tapi Intoleran
Akar dari melemahnya komitmen perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di negara ini sebenarnya sudah tampak sejak masa pemerintahan sebelumnya, Joko Widodo.
Beberapa pakar seperti Marcus Mietzner menyebut bahwa politik Indonesia mengalami proses kemunduran demokrasi dan penguatan otoritarianisme yang berdampak langsung pada melemahnya komitmen pemerintah dalam menjamin hak-hak sipil.
Keterkaitan antara otokratisasi dan intoleransi ini digambarkan dalam istilah “productive intolerance” oleh Jeremy Menchik, fenomena di mana intoleransi justru menjadi alat atau mekanisme yang menghasilkan atau mendukung sistem otokratis.
Dalam konteks ini, intoleransi tidak hanya sebagai sikap negatif terhadap perbedaan, tapi berfungsi secara aktif untuk mengonsolidasikan kekuasaan otoriter dengan menekan oposisi atau menindas kelompok lain sembari memperkuat dominasi kelompok tertentu.
Praktik ini semakin dimungkinkan dengan kehadiran “intoleran democrat”, yaitu para politikus yang terpilih melalui proses demokratis namun melanggengkan praktik intoleran.
Dinamika Politik Lokal
Dinamika politik lokal juga sangat berperan dalam merangsang atau menekan tumbuhnya intoleransi.
Indeks Kota Toleran yang dikembangkan oleh SETARA Institute memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengaruh dari ekosistem politik lokal terhadap kondisi toleransi di satu wilayah.
Dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh SETARA Institute pada Mei 2025, hanya ada 10 kota yang dianggap berhasil menjaga iklim keberagaman. Mereka menerapkan aturan daerah yang mampu mencegah radikalisme, diskriminasi, serta kekerasan terhadap kelompok minoritas.
Laporan yang sama menyebutkan, alokasi anggaran untuk inisiatif kegiatan sosial lintas iman oleh pemerintah daerah berperan dalam memperkuat ekosistem toleransi di beberapa kota, seperti yang dilakukan di Salatiga dan Semarang.
Sebaliknya, jika elite politik yang didukung kelompok intoleran menang, patronase antara elite politik dan kelompok intoleran cenderung berlanjut. Beberapa daerah yang masuk dalam kategori intoleran adalah beberapa kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, seperti Banda Aceh, Lhoksumawe, dan Sabang.
Selain ketiadaan kepemimpinan politik dan inisiatif birokratis dalam memungkinkan kehidupan yang toleran, konsepsi kewarganegaraan di Aceh dibangun atas dasar dorman citizenship, di mana kaum muslim dianggap sebagai warga negara utama yang menjadi tuan rumah di provinsi yang menerapkan syariah; sedangkan yang non-muslim menjadi warganegara kelas kedua, sehingga diskriminasi terhadap minoritas tak terhindarkan.
Klientelisme Politik
Adanya hubungan klientelistik antara elite politik lokal dan rakyat di beberapa daerah, terutama pada masa pemilihan daerah, menyuburkan intoleransi dalam sistem yang makin otoriter.
Sebuah penelitian yang dilakukan di Tasikmalaya menunjukkan bahwa banyak jemaat Ahmadiyah kesulitan mengakses jasa publik dan perlindungan dari pemerintah karena adanya kontrak politik antara pemimpin daerah dengan tokoh agama anti-Ahmadiyah.
Praktik serupa juga terjadi di Aceh. Klientelisme politik antara elite dan ulama dari dayah (pesantren tradisional) membuka ruang bagi lahirnya praktik intoleransi yang bersifat sektarian seperti fatwa yang membatasi kegiatan keagamaan kelompok Salafi.
Penelitian lain yang menelisik persepsi umat muslim terhadap etnis Tionghoa di Indonesia juga menunjukkan bahwa sikap intoleransi sering dimobilisasi dengan adanya hubungan klientelistik antar religio-political entrepreneur dengan beberapa segmen masyarakat muslim di Indonesia.
Penelitian ini menyebutkan bahwa sikap anti-minoritas merupakan sikap yang melekat di kelompok politik Islamis, yang berpengaruh pada bagaimana masyarakat muslim di Indonesia menyikapi isu pengadilan Basuki Tjahaja Purnama pada 2016.
Moderasi Semu
Moderasi awalnya ditawarkan sebagai narasi untuk menangkal radikalisasi di tengah masyarakat pada awal tahun 2000-an. Saat itu, Indonesia menghadapi serangkaian serangan teror yang digerakkan oleh beberapa individu yang terpengaruh ide-ide radikal.
Ide-ide moderasi keberagamaan kemudian mulai dilembagakan di masa kepresidenan Megawati Sukarnoputri melalui 1st International Conference of Islamic Scholars (ICIS) pada 2004. Namun, pelembagaan ini banyak tersandung hambatan domestik dengan adanya kasus diskriminasi keagamaan yang begitu marak dan pengaruh politik keagamaan yang kuat di Indonesia.
Di era Joko Widodo, moderasi keberagamaan diperkuat dengan pendirian lembaga seperti BPIP dan institusionalisasi praktik moderasi di Kementerian Agama melalui pendirian rumah moderasi.
Akhir-akhir ini, Kementerian Agama di era Prabowo juga menawarkan gagasan Kurikulum Cinta untuk membuat moderasi bisa dipahami tidak hanya sebagai konsep, namun juga sebagai sikap hidup. Jika melihat indikator yang dirilis oleh Pew Research Center pada 2024, Indonesia masih memiliki tingkat Government Restriction Index yang amat tinggi di angka 7,9 dan tingkat Social Hostility Index yang tinggi di angka 4,7.
Memang, jika dibandingkan dengan indeks dari tahun 2007, Indonesia telah mengalami perbaikan dalam kedua indeks dalam isu pembatasan pemerintah dalam KBB serta indeks kekerasan sosial.
Namun, tidak adanya perubahan cara pandang moderasi yang masih berbasis kontrol dominan negara dalam pengelolaan agama tidak akan menyelesaikan persoalan intoleransi.
Menyemai Solidaritas Dari Bawah
Praktik-praktik solidaritas antaragama dan intra-agama dimungkinkan oleh adanya peran kolaboratif antara aktor negara dan masyarakat. Negara perlu hadir sebagai penjamin kebebasan beragama, bukan hanya sebagai tukang ronda yang hanya menindak kasus-kasus pelanggaran kebebasan tersebut ketika terjadi.
Inisiatif bersifat organik, seperti membuka ruang perjumpaan antar komunitas antaragama dan intra-agama, penguatan solidaritas sosial melalui kolaborasi kegiatan, serta pengenalan keberagaman agama sejak dini, dapat membantu memperkuat toleransi dan solidaritas antar warga.
Tulisan sudah dimuat di The Conversation Indonesia pada 1 Agustus 2025
Hadza Min Fadhli Robby
Dosen Jurusan Hubungan Internasional UII. Pengamat politik Turki dan India. Bidang riset pada gagasan politik Islam, studi agama dalam Hubungan Internasional.