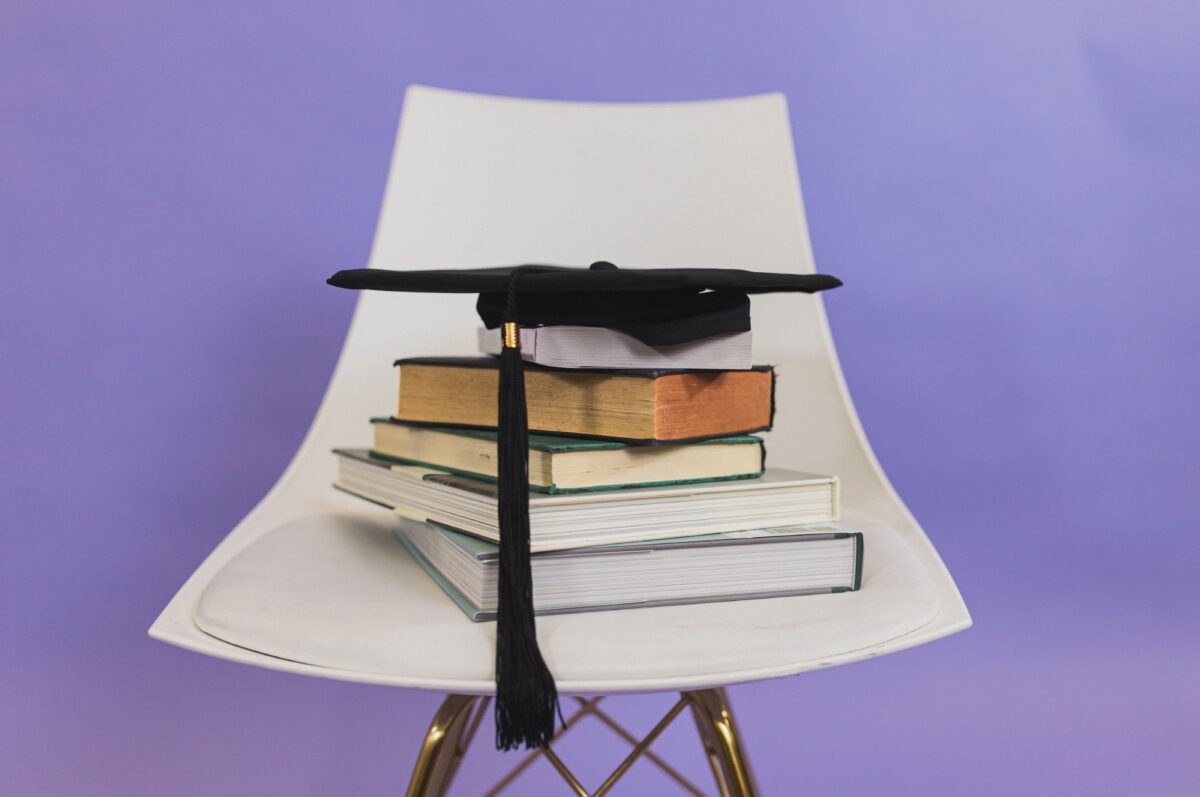- Pernyataan Sri Mulyani soal gaji guru dan dosen memicu perdebatan tentang tanggung jawab negara dalam pendanaan pendidikan.
- Pendidikan adalah hak publik, tapi dalam praktiknya kerap terjebak pada logika efisiensi, komersialisasi, dan orientasi pasar.
- Pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk membentuk warga negara yang cakap, kritis, dan beretika.
Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mempertanyakan apakah gaji guru dan dosen harus sepenuhnya ditanggung negara Kamis, 7 Agustus 2025 lalu memantik diskusi publik yang sengit.
Di satu sisi, komentar tersebut menyingkap keresahan fiskal. Di sisi lain, ini membuka ruang kritik terhadap pendidik yang menuntut hak kesejahteraan.
Konstitusi sebenarnya memandatkan pernyataan tersebut dengan jelas. Pasal 31 UUD 1945 mewajibkan negara mengalokasikan minimal 20% APBN untuk pendidikan (senilai Rp724,3 triliun pada tahun anggaran 2025). Selain itu, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan pendidikan sebagai hak warga negara dan kewajiban pemerintah.
Negara mengalokasikan minimal 20% APBN untuk pendidikan. Tapi jumlah tersebut termasuk untuk membiayai program makan siang gratis. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, idealisme ini kerap tergerus keterbatasan anggaran, birokrasi kaku, dan salah arah orientasi kebijakan.
Total alokasi duit negara untuk pendidikan sebesar Rp700 triliunan memang besar. Tapi jangan lupa jumlah tersebut harus disunat untuk membiayai program makan siang gratis. Bagaimana seharusnya negara menempatkan diri dalam melihat pendanaan pendidikan?
Fungsi pendidikan dan tantangan implementasi
Gert Biesta, ahli teori pendidikan dari Belanda, menawarkan tiga fungsi pendidikan yakni kualifikasi (membekali pengetahuan/keahlian untuk berpartisipasi dalam kerja dan warga-negara), sosialisasi (mentransmisikan nilai/norma agar menjadi bagian tatanan sosial), dan subjektifikasi (membentuk pribadi otonom, kritis, bertanggung jawab).
Masalahnya, kebijakan sering bias pada kualifikasi terkait pengukuran keberhasilan lewat kelulusan, skor, dan penempatan kerja. Sementara sosialisasi dan subjektifikasi menyusut karena tekanan efisiensi dan komersialisasi.
Akibatnya, kurikulum kerap dipersempit. Ini menyebabkan pengesampingan “aspek non-tes seperti seni dan keterampilan sosial”, relasi dosen–mahasiswa yang transaksional, dan ruang mengkritisi kebijakan publik yang semakin sedikit.
Dampaknya, pendidikan kehilangan perannya dalam membentuk karakter, etika, dan kemampuan reflektif, serta gagal menumbuhkan keberanian moral untuk mempertanyakan ketimpangan di masyarakat.
Antara pasar dan pengetahuan
Setiap negara memiliki tiga tipologi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat global yaitu sebagai aset nasional, hak publik, dan komoditas.
Di negara Nordik seperti Swedia dan Finlandia, pendidikan dipandang sebagai public good yang menjadi hak setiap warga dan ditanggung sepenuhnya oleh negara. Model ini jarang digunakan di Indonesia, meski prinsipnya tertulis dalam konstitusi.
Dari kacamata sejarah, perjalanan pendidikan tinggi di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga fase besar. Pertama pada fase era kolonial sebelum 1945, pendidikan dirancang sebagai instrumen kepentingan kekuasaan, memproduksi elit birokrasi yang melayani administrasi penjajah.
Fase kedua pada era Perang Dingin (1945–1990), pendidikan menjadi arena perebutan pengaruh ideologi. Beasiswa dan program pertukaran seperti Fulbright dan Monbukagakusho digunakan untuk membentuk teknokrat dan pemimpin yang selaras dengan blok politik tertentu.
Setelah itu, fase ketiga terjadi pada krisis finansial Asia 1997 yang menandai masuknya era neoliberal. Privatisasi, deregulasi, dan logika pasar mulai mendominasi pendidikan tinggi.
Fase terakhir ini tampak jelas terjadi di Indonesia dengan meningkatnya praktik komodifikasi yang seolah menjadikan pendidikan tinggi sebagai “aktivitas pencetak uang.”
Pemeringkatan kampus pun menjadi obsesi baru. Indikator kuantitatif seperti jumlah publikasi sering kali mengalahkan misi pendidikan itu sendiri. Kompetisi antaruniversitas pun kerap berubah menjadi perlombaan kosong yang menguras sumber daya, sementara orientasi komersial merambah ke banyak aspek, mulai dari kurikulum yang disesuaikan tren pasar hingga layanan kampus yang dibungkus seperti produk.
Orientasi ini selaras dengan model komoditas yang marak di negara Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris, meskipun fungsi publiknya belum sepenuhnya hilang.
Inggris menunjukkan pendekatan hibrida: mempertahankan pendanaan publik untuk riset (warisan model aset nasional) sambil menerapkan logika komoditas pada biaya kuliah. Bahkan di AS, yang kerap dijadikan contoh sistem terpasarkan, universitas masih menjalankan fungsi publik seperti riset dasar dan pelayanan masyarakat.
Kasus seragam dapat ditemukan pada negara lain di Global Selatan, seperti Malaysia dan India.
Pada dua negara tersebut, meskipun arus alokasi dana negara kian berkurang, standar kualifikasi pendidikan tinggi yang bermutu tetap dapat dipertahankan. Negara tetap menjadi aktor prominen dalam sistem pendidikan tinggi, terkhusus dalam kewajibannya menangani problem struktural.
Pendidikan sebagai investasi, bukan pengeluaran
Jika pendidikan terus dipandang hanya sebagai variabel biaya, kita berisiko kehilangan orientasi jangka panjang. Penjaminan pendanaan guru dan dosen bukanlah tindakan amal tapi investasi institusional untuk menghasilkan warga negara yang cakap, beretika, dan kritis.
Pengalaman internasional menunjukkan, peran negara dalam pendidikan tinggi tetap krusial, bahkan di sistem yang sangat berorientasi pasar.
Meski demikian, kontribusi Sri Mulyani melalui pendirian Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) layak diapresiasi karena berhasil memperluas akses beasiswa bagi puluhan ribu pelajar Indonesia. Inisiatif ini menunjukkan adanya investasi jangka panjang, meski aspek pendanaan rutin pendidikan masih menyisakan pekerjaan rumah.
Partisipasi masyarakat, baik melalui filantropi, dana abadi, maupun kemitraan publik–swasta, bisa menjadi pelengkap yang memperkuat kapasitas negara. Namun, partisipasi itu tidak boleh menggantikan komitmen publik yang telah dijamin konstitusi.
Instrumen negara dalam memperluas akses pendidikan tinggi, utamanya bagi kalangan menengah ke bawah, dan menekan naiknya biaya kuliah akibat inflasi perlu dioptimalisasi. Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibebankan pada masyarakat bisa dinilai sebagai sikap abai negara dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan.
Membawa kembali pendidikan pada tiga fungsinya adalah langkah kunci agar kebijakan tidak terjebak pada logika untung-rugi. Dengan keseimbangan yang tepat, pendidikan akan kembali ke hakikatnya: memenuhi amanah konstitusi, memperkuat daya saing, dan membangun peradaban.
Jangan sampai, Indonesia makin terpuruk hanya karena beban fiskal sedang tersedot ke pos-pos pengeluaran tertentu, apalagi merespons secara reaktif dengan mengundang partisipasi masyarakat.
Penggunaan istilah “partisipasi dari masyarakat” juga ironis. Sebab, masyarakat adalah pembayar pajak yang sudah, sedang, dan akan selalu berpartisipasi dalam pembangunan manusia.
Faktanya, berdasarkan data 2023, kontribusi UKT terhadap pendapatan operasional kampus sangat signifikan. UKT menyumbang 77% dari total pendapatan Universitas Indonesia. Angka di Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung masing-masing sekitar 52%, 42%, dan 32%.
Artinya, masyarakat (pembayar pajak maupun mahasiswa) bukan hanya sekadar berpartisipasi, melainkan telah menjadi investor utama yang menopang keberlangsungan pendidikan tinggi.
Tulisan ini sudah dimuat di The Conversation Indonesia pada tanggal 21 Agustus 2025
Hangga Fathana
Dosen Jurusan Hubungan Internasional UII. Minat riset pada politik ekonomi global, politik perdagangan, dan dinamika perkembangan kapitalisme.