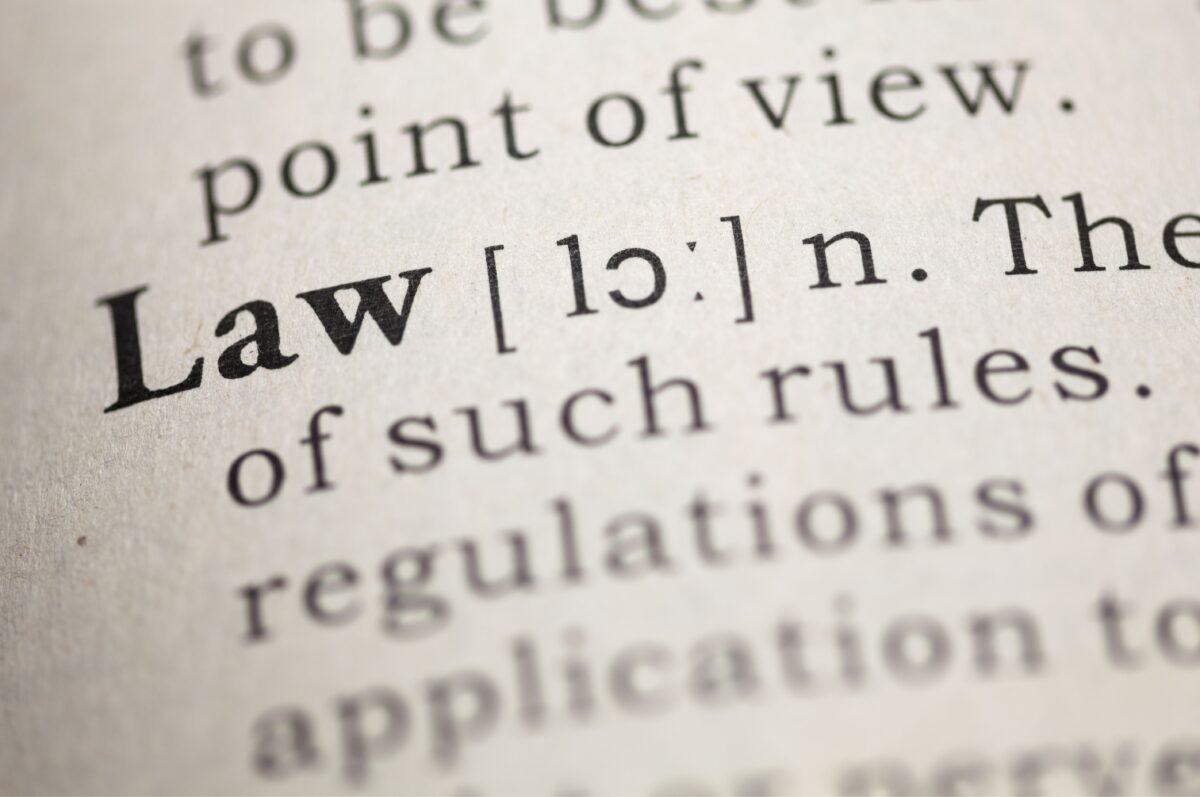Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali dipersoalkan, bahkan Presiden Prabowo secara implisit menginginkan agar Pilkada dikembalikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pilkada melalui DPRD sesunggunya bukan isu baru. Pasca reformasi sampai tahun 2005 Indonesia menerapkan Pilkada melalui DPRD. Baru setelah tahun 2005, melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang saat ini menjadi Pilkada serentak dan langsung. Tahun 2014 lalu, DPR-RI dan Pemerintah pernah menyetujui penyelenggaraan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, namun hanya sehari setelahnya, UU ini dibatalkan oleh Presiden SBY melalui Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu).
Kalau ditelisik lebih dalam, wacana mengembalikan Pilkada oleh DPRD bukan tanpa alasan sama sekali. Pertama, secara sederhana penyelenggaraan Pilkada langsung membutuhkan cost atau biaya yang jauh lebih tinggi. Mulai dari percetakan kertas suara, distribusi kertas suara, pembentukan TPS, akomodasi panitia pemilihan dan pengawas, gaji panitia dari level kecamatan, desa, hingga TPS, dan masih banyak kebutuhan lain yang sangat besar.
Kedua, fenomena calon tunggal yang melawan kotak kosong semakin menguat setiap kali penyelenggaraan Pilkada. Harus dipahami, Pilkada secara langsung sedikit banyak berkontribusi atas kondisi ini, karena biaya politik yang tinggi menyebabkan partai politik enggan mengusung calon di daerah tertentu. Ketiga, apa yang cukup mengkhawatirkan dalam penyelenggaraan Pilkada langsung adalah menguatnya segregasi sosial, terutama beberapa daerah yang masih menggunakan dan memanfaatkan sentimen religius dan suku dalam mendulang elektabilitas.
Keempat, berbanding lurus dengan itu, adalah tingkat literasi masyarakat, terutama literasi politik yang masih lemah. Jika kita petakan, atau setidaknya telusuri melalui kajian Aspinal 2019 lalu, mayoritas masyarakat sama sekali tidak melihat rekam jejak calon dalam menentukan pilihan, namun digerakkan oleh money politics tim sukses. Artinya, pemilih tidak memilih berdasarkan hati nuraninya, dan calon tidak perlu menunjukkan rekam jejak dan prestasinya, semua dikendalikan oleh politik uang. Pemilu tahun 2024 ini, tampaknya keempat komponen ini bukan saja masih terjadi, tapi justru semakin memburuk.
Wacana Pemilihan Tidak Langsung
Pemilihan kepala daerah oleh DPRD atau tidak langsung, sebetulnya bukan-lah pilihan ideal. Sebagaimana pengalaman masa lalu Indonesia, Pilkada oleh DPRD sangat rentan dikooptasi atau dibajak oleh kepentingan politik penguasa. Dengan jumlah yang lebih sedikit, tentu akan lebih mudah mengendalikan anggota DPRD dari pada masyarakat luas. Maka, adalah rahasia umum jika money politics saat itu juga beredar, namun hanya di kalangan anggota DPRD dan partai politik.
Belum lagi, sekalipun dalam konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) hanya menyebut pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, artinya tidak menyebut langsung maupun tidak langsung, namun perjalanan putusan MK secara konstitusional telah sampai pada penyatuatapan rezim Pilkada ke dalam pemilihan umum, sehingga juga diselenggarakan langsung oleh rakyat. Belum lagi, kalau kita membaca UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD didesain dengan sangat lemah. DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah, bukan lembaga legislatif di daerah. Artinya, sangat tidak konsisten dengan desain awal jika Pilkada diserahkan kepada DPRD. Selain itu, mengembalikan Pilkada kepada DPRD pasti akan berujung pada penolakan rakyat, demo akan terjadi di mana-mana, belum lagi judicial review terhadap Mahkamah Konstitusi (MK).
Karena itu, tulisan ini sampai pada kesimpulan bahwa wacana mengembalikan Pilkada oleh DPRD ini jangan dibaca semata-mata hanya pilihan politik praktis elite. Kita tahu betul, Pilkada langsung saat ini melahirkan berbagai persoalan serius yang memperkuat segregasi sosial.
Isu mengembalikan Pilkada oleh DPRD harus menjadi alarm kuat, bahwa ada masalah pelik dengan pilkada langsung saat ini. Harus ada solusi agar sentimen identitas tidak lagi digunakan, money politics ditekan, politisasi lembaga negara (ASN, TNI, dan Polri) dihentikan, dan yang terutama adalah melembagakan literasi politik kepada seluruh masyarakat. Mengubah desain Pilkada bukanlah solusi, sebagaimana pengalaman dan perjalanan panjang Republik ini.
Tulisan sudah dimuat di rubrik Opini Kedaulatan Rakyat pada tanggal 24 Oktober 2025
Despan Heryansyah
Dosen Fakultas Hukum UII dan Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK). Bidang riset pada hak asasi manusia dan kebijakan publik, hak-hak kelompok rentan, dan pemerintahan daerah. Penelitiannya berfokus pada isu hak penyandang disabilitas, perempuan, dan anak, otonomi daerah, dan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan.