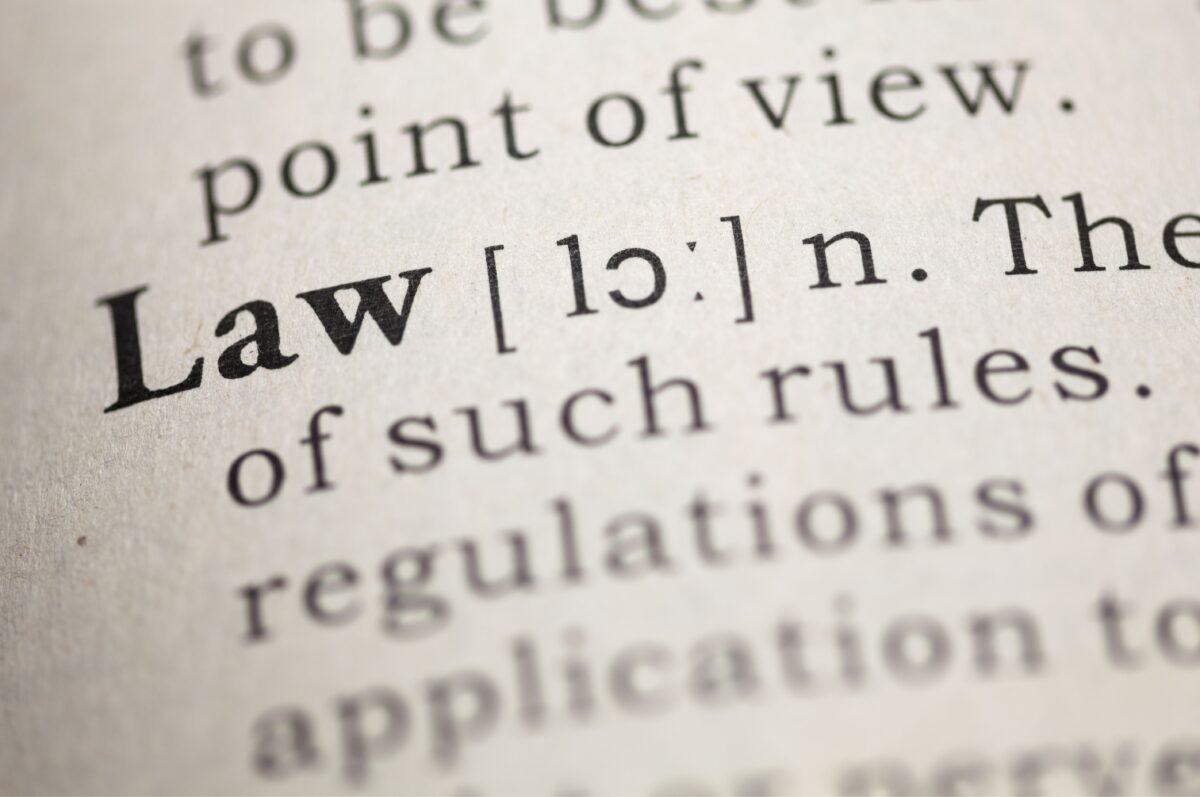Masalah etika dan akademis para dosen untuk mencapai status ‘profesor’ atau ‘guru besar’ belakangan ini menjadi sorotan publik. Perkara-perkara mulai dari kontroversi guru besar muda, Kumba Digdowiseiso, praktik “aji mumpung” kampus untuk mengatrol guru besar, hingga para politikus yang berlomba-lomba mendapatkan gelar profesor, menggerus kredibilitas akademisi berikut kebijakan pemerintah seputar penilaian akademis di mata publik.
Di tengah persoalan tersebut, terbit surat edaran dari Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Fathul Wahid, yang meminta agar gelar akademisnya tidak dicantumkan di dalam surat, dokumen, serta produk hukum kampusnya. Rektor UII hanya mengecualikan edaran “jangan panggil saya Prof” ini untuk dokumen ijazah dan transkrip nilai.
Tradisi menanggalkan penyematan gelar dalam pergaulan akademis memang bukan praktik baru di banyak negara. Namun, di Indonesia, langkah rektor UII dapat kita lihat sebagai sebuah gerakan simbolik untuk membuka diskusi seputar desakralisasi gelar akademis di tengah fenomena inflasi guru besar di tanah air.
Sakralisasi gelar akademis
Di Indonesia, pencapaian gelar akademis maupun atribut lainnya sering terkait dengan motivasi ekonomi terutama kenaikan gaji dan tunjangan. Pencapaian juga menjadi simbol mobilitas vertikal untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan istimewa dalam masyarakat. Akibatnya, banyak orang mengejar gelar tersebut dengan menempuh berbagai siasat.
Ini dibuktikan dengan temuan penelitian yang menempatkan integritas publikasi ilmiah di Indonesia terendah nomor dua di dunia. Dalam hal ketidakjujuran akademis, skor Indonesia hanya 16,7%, di bawah Kazakhstan yang menempati urutan pertama (17%).
Di sisi lain, tradisi pengultusan hierarki profesor sebagai derajat akademis tertinggi semakin menguatkan budaya feodalisme sekaligus peneguh kesenjangan. Alih-alih merujuk pada tanggung jawab keilmuan dan kepakaran, gelar doktor atau profesor kerap secara sengaja disakralkan untuk memperlebar jarak sosial, termasuk di lingkungan kampus.
Penunjukan jabatan seperti kepala pusat studi di kampus, misalnya, sering kali berdasarkan pengutamaan status profesor, bukan berdasarkan kualitas individu dan rekam kinerja riset.
Para pemilik gelar mungkin tidak menyadari ataupun mengakui sakralisasi ini. Namun, tetap saja, masih ada profesor yang tersinggung jika gelarnya tidak ditulis dalam surat undangan ataupun merasa direndahkan jika orang lain memanggil namanya tanpa disertai sapaan “Prof”.
Antara budaya feodal dan iklim akademis yang egaliter
Harus diakui, tradisi akademis terkait panggilan profesor diterapkan secara berbeda di Indonesia atau secara umum di Asia, jika dibandingkan negara Barat.
Ini salah satunya bersumber pada kentalnya budaya paguyuban (gemeinschaft) yang merupakan ciri masyarakat feodal bercorak produksi agraris–pedesaan. Budaya paguyuban berdasar pada hubungan status seperti keluarga, tradisi, dan adat yang menempatkan kendali dan hormat kepada para senior atau mereka yang dianggap dituakan.
Namun, iklim akademis dan budaya intelektual di perguruan tinggi semestinya bersifat egaliter dan kolegial. Alexander Kapp, seorang pendidik dari Jerman, pada tahun 1833 memperkenalkan pendekatan andragogi yang kemudian dikembangkan menjadi teori pendidikan orang dewasa oleh pendidik Amerika Serikat (AS), Malcolm Knowles. Andragogi adalah proses pelibatan peserta didik dewasa ke dalam pengalaman belajar dengan model interaksi egaliter antara mahasiswa dengan dosennya sebagai sesama orang dewasa.
Artinya, berdasarkan pendekatan andragogi, lembaga pendidikan tinggi diharapkan terus melahirkan para ahli dengan cara bertukar pikiran secara proporsional, asertif, kritis, dialogis, dan kolegial. Pelaksanaan cara ini pun harus berlandaskan sikap saling menghargai serta menghormati tata nilai dan budaya akademis yang berlaku universal.
Bentuk pengultusan seperti rasa segan dan hormat yang berlebihan, jika hanya didasarkan pada superioritas gelar, bukan pada kapasitas keilmuan dan rekam jejak akademis, akan menghambat perkembangan iklim akademis dan budaya intelektual yang sehat di kampus.
Upaya desakralisasi
Sebelum Rektor UII, banyak tokoh dan akademisi di tanah air yang juga menerapkan praktik sapaan egaliter. Mendiang Ahmad Syafii Maarif, misalnya, jarang menuliskan gelar akademisnya. Meski telah didapuk sebagai “tokoh bangsa” dan pernah menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ia lebih nyaman dipanggil “Buya” daripada gelar berderet “Prof. K.H. Ahmad Syafii Maarif, M.A, Ph.D”.
Contoh lain akademisi asal Indonesia yang konsisten menolak dipanggil “Prof” adalah sosiolog Ariel Heryanto. Ia selalu mengatakan, “Panggil saja saya Ariel,” kepada orang-orang yang memanggilnya dengan sapaan “Prof Ariel”.
Belakangan, beberapa instansi terkait pendidikan dan riset di Indonesia seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga tidak lagi menuliskan gelar akademis dalam standar pengesahan dokumen-dokumen resmi.
Lebih dari sekadar panggilan
Akar masalah integritas akademis di Indonesia bukanlah terbatas pada perlu-tidaknya panggilan-penulisan, desakralisasi, atau sebaliknya pemurnian gelar “profesor”.
Kejujuran, kedisiplinan, etika, dan integritas akademis perlu segera ditegakkan oleh semua pihak, lebih dari sekadar perlu atau tidaknya atribusi bagi seorang profesor.
Banyak persoalan integritas akademis dalam proses pengajuan guru besar yang juga perlu disorot. Sebut saja kelayakan dan riwayat integritas akademis individu pengaju jabatan guru besar, independensi asesor administratif dan substantif, impunitas (pembebasan dari hukuman) terhadap pelaku perjokian dan praktik predatory karya ilmiah, dan normalisasi plagiarisme. Kita juga perlu mengawasi kurangnya transparansi, kecepatan merespons dan menangani kasus, serta ketegasan penegakan aturan disiplin etika akademis oleh institusi pengelola yaitu pihak kampus dan Kemendikbudristek.
Gerakan moral desakralisasi gelar profesor ini telah diinisiasi oleh Rektor UII, dan ternyata berhasil menarik perhatian publik lebih luas. Oleh karena itu, mengapa tidak kita dukung sebagai momentum untuk berbenah?
Tulisan sudah dimuat di The Conversation Indonesia pada tanggal 23 Juli 2024
Iwan Awaluddin Yusuf
Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi UII. Bidang riset pada jurnalisme, gender, media digital dan superhero sebagai budaya pop.