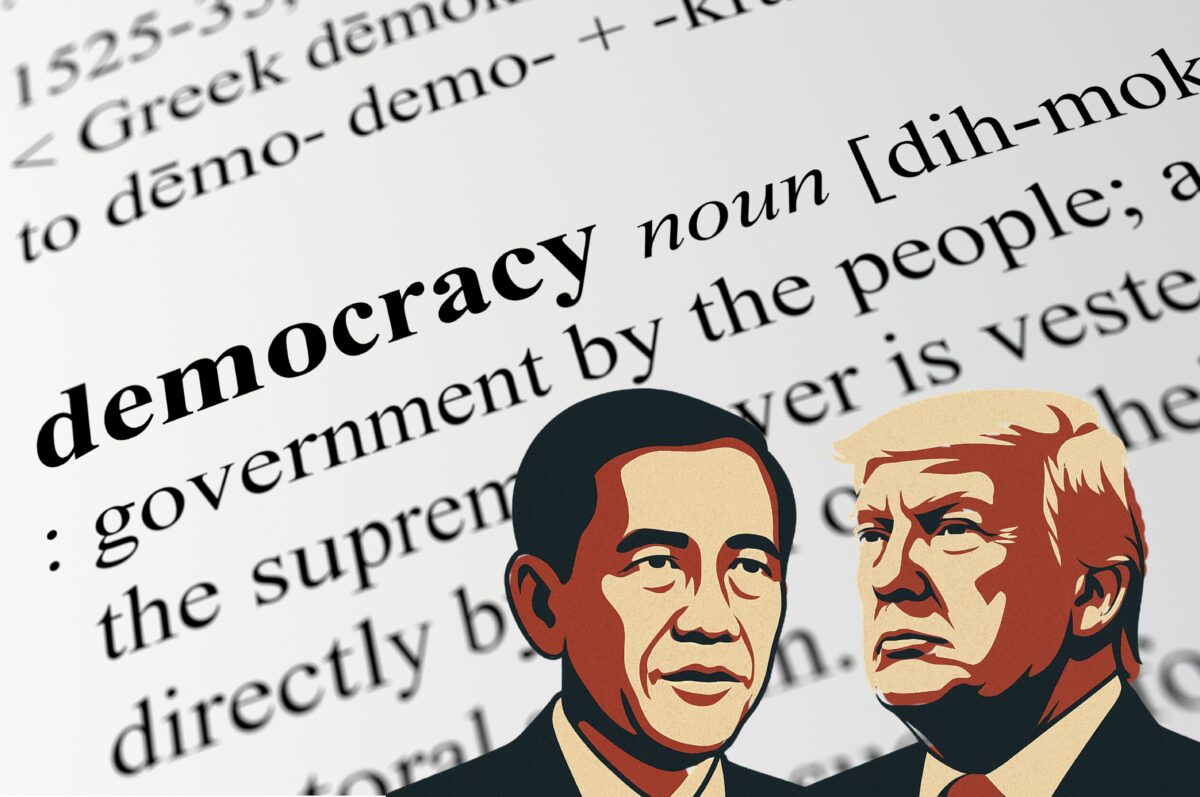Dalam sebuah demokrasi yang sehat, pemerintahan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Pernahkah Anda mendengar nama Hugo Chavez? Dia adalah pemimpin otoriter Venezuela dari tahun 1999 hingga tahun 2013.
Chavez menjadi otoriter setelah secara demokratis terpilih menjadi pemimpin negara Amerika Latin tersebut. Proses menuju otoritarianisme tersebut melalui beberapa proses: penghancuran nilai-nilai demokrasi, penggunaan taktik-taktik otoriter, polarisasi politik, erosi institusi demokrasi, pembungkaman media, dan kejadiannya terjadi secara berangsur-angsur. Kita patut mewaspadai tanda-tanda proses tersebut agar kita bisa mengawal negara kita sendiri untuk tidak kembali pada otoritarianisme.
Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, terpilih secara demokratis pada Pemilu tahun 2024. Dalam proses pencalonannya, hukum di Indonesia disesuaikan secara legal untuk melancarkan pencalonan wakilnya, Gibran, anak dari presiden sebelumnya, Joko Widodo.
Masyarakat mengingat bagaimana kasus ini bergulir di MK serta dinamikanya yang cukup mencuri perhatian masyarakat. Salah satunya terkait dengan usia minimum untuk dapat menjadi wakil presiden. Beberapa ahli, seperti Muhammad Tri Adika berpendapat bahwa Gibran menjadi kendaraan Prabowo untuk mendapatkan hati pendukung Joko Widodo di daerah-daerah di Indonesia. Demokrasi biasanya mati secara perlahan bukan karena kudeta.
Pada tahun 2025, ketika Prabowo dilantik menjadi presiden, dalam politik Tanah Air, kita dapat melihat terlemahkannya toleransi antar aktor politik dan antar masyarakat, serta nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Kabinet gemuk yang dimiliki saat ini menunjukkan bagaimana oposisi hampir-hampir ditiadakan. Partai-partai pendukung Anies kini masuk ke rombongan besar ini. Dan hanya PDIP yang nampak berperan sebagai oposisi di tengah pemerintah.
Meskipun kita dapat mengkritisi kader-kader tindakan PDIP yang sempat tidak mengikuti retret kepala daerah karena kepala daerah adalah petugas rakyat dan bukan hanya petugas partai, kita bisa berargumen bahwa ada indikasi gaslighting yang dilakukan oleh pemerintahan pemegang kuasa dalam hal tersebut.
Dalam sebuah demokrasi yang sehat, pemerintahan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, kebijakan juga seharusnya berpihak pada rakyat. Akan tetapi, kejadian ironis di kala seorang ayah di-PHK demi efisiensi dan pajak negara digunakan untuk Program Makan Siang Gratis.
Hal ini mungkin terjadi karena adanya miskoordinasi di dalam badan-badan milik pemerintah. Dalam kesempatan lain, pemerintah, dianggap oleh beberapa kalangan, membungkan kebebasan pelukis dan musisi yang menyuarakan kritik mereka melalui karya seni, seperti lagu “Bayar, bayar, bayar” dan lukisan “Tikus Garuda” yang “diamankan”. Namun, hal ini bisa saja terjadi karena koordinasi dan komunikasi yang kurang lancar. Bagaimanapun itu, kita perlu melihat seperti apa sebenarnya kasus ini bergulir.
Jika kita pantau lebih lanjut dan membandingkan apa yang terjadi di Indonesia dengan apa yang terjadi di Venezuela pada masa awal Hugo Chavez, kita bisa melihat persamaan penafikan aturan demokrasi, penolakan legitimasi lawan, penggunaan kekerasan, dan pengebirian kebebasan sipil.
Kita sedang menyaksikan mahasiswa dianggap “gaduh” dan “mengganggu” ketika sedang berunjuk rasa menolak pemotongan anggaran pendidikan. Kemudian hampir tiadanya oposisi di dalam pemerintahan, represi pada protes menentang Program Makan Siang Gratis oleh orang-orang Papua, serta pembungkaman secara halus akademisi, seniman, dan media melalui cara-cara seperti pengelolaan tambang.
Hal-hal tersebut adalah awal mula dari melemahnya demokrasi di negara ini. Bisa saja ada oknum yang menggunakan kekuasannya untuk memperkeruh suasana. Kita perlu duduk sebentar dan merenunginya, kemudian mempertayakan, apa yang sebenarnya terjadi.
Selanjutnya, institusi-institusi di pemerintahan mulai memperlihatkan perlemahan demokrasi dan kurangnya check and balances antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di negara ini. Eksekutif dapat mengeluarkan aturan dan program dengan mendapatkan persetujuan dari DPR. DPR kita saat ini sudah didominasi oleh partai-partai pendukung pemerintah.
Dan peraturan-peraturan kini dapat diubah melalui Mahkamah Konstitusi. Hampir tidak adanya oposisi akan berakibat pada tidak adanya pihak yang mengawasi kinerja pemerintah. Memang, dalam praktiknya, kondisi yang demikian itu akan lebih melancarkan program-program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat jika dijalankan oleh orang-orang yang berintegritas dan berkomitmen untuk pembangunan bangsa. Akan tetapi, dengan minimnya check and balances tersebut, rakyat dapat menjadi pihak yang senantiasa mengawasi pemerintah secara langsung, agar oknum-oknum nakal dapat diminimalisasi.
Ketika aktor pemerintahan tidak bisa lagi mengawasi jalannya pemerintahan, Masyarakat melalui media (cetak, elektronik, maupun sosial), adalah cara berikutnya untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Sayangnya pada masa ini, algoritma dalam penggunaan media sosial atau elektronik sudah membuat semacam gelembung informasi. Seorang hanya akan mendengar atau menyaksikan informasi sesuai dengan kesukaan dan kebutuhannya saja, bukan informasi yang memang dia perlu untuk ketahui.
Sekarang ini pula, suatu berita tidak akan langsung dapat dikonsumsi atau disaksikan oleh masyarakat. Seorang pasangan yang tinggal dalam satu rumah saja dapat memperoleh narasi yang berbeda atas suatu kejadian berdasarkan algoritma yang mereka terima. Penyebaran informasi menjadi tidak merata.
Dengan kondisi saat ini, kesadaran masyarakat terhadap media yang kredibel mulai tergantikan oleh media sosial. Sehingga, Masyarakat kehilangan kesempatan untuk mengkritisi sesuatu yang mereka tidak ketahui. Situasi ini membuat pemerintah, tidak perlu bersusah payah membatasi peran media di Masyarakat seperti yang terjadi di Venezuela pada era 2000-an.
Penggunaan buzzer juga menjadi sarana untuk melawan isu yang beredar di masyarakat seperti dalam kasus protes Indonesia Gelap yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Sudah seharusnya, kita menjadi lebih kritis terhadap apa yang pemerintah laksanakan. Dengan demikian, kita bersama dengan pemerintah, dapat membangun Indonesia menjadi negeri yang lebih maju.
Dari kenyataan yang kita hadapi saat ini, kita dapat mulai mewaspadai pihak-pihak yang dapat mengancam keberlangsungan kebebasan dan demokrasi di negara ini. Berkaca pada Hugo Chavez, bibit-bibit penghancuran nilai-nilai demokrasi, penggunaan taktik-taktik otoriter, polarisasi politik, erosi institusi demokrasi, dan pengebirian media sedikit demi sedikit sudah mulai terlihat. Kita harus dapat waspada dan terus mengawasi orang-orang yang berkuasa agar Indonesia dapat tetap maju menjadi bangsa yang menyejahterakan masyarakatnya.
Tulisan sudah dimuat di rubrik opini Republika pada tanggal 3 Maret 2025
Mohamad Rezky Utama
Minat penelitian berfokus pada diplomasi, politik identitas, politik keagamaan, kebijakan luar negeri, Timur Tengah, dan kelompok kepentingan internasional. Bidang keahlian meliputi Politik Timur Tengah serta Aliran Keagamaan dan Politik.





 Sementara dalam konser musik, mulai dari pop sampai dangdut, biasanya ada anggota TNI berseragam lengkap turut berjaga di tengah keramaian.
Sementara dalam konser musik, mulai dari pop sampai dangdut, biasanya ada anggota TNI berseragam lengkap turut berjaga di tengah keramaian.