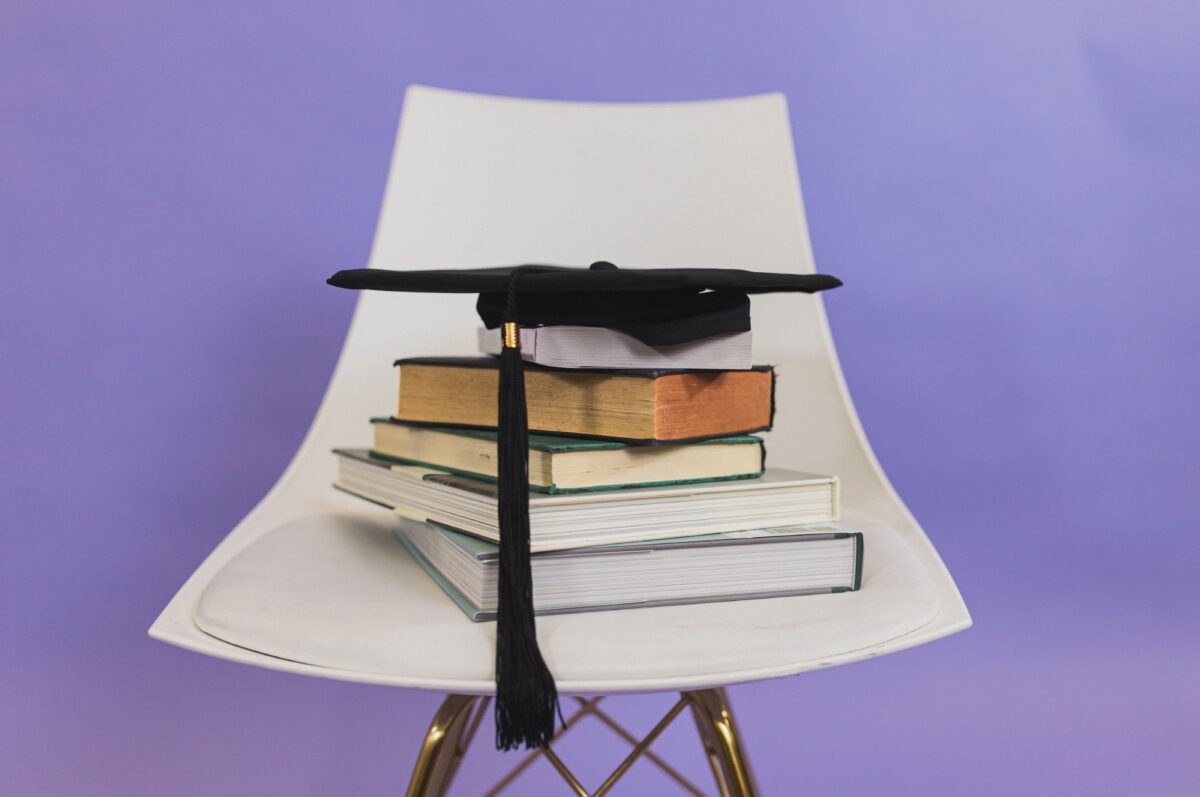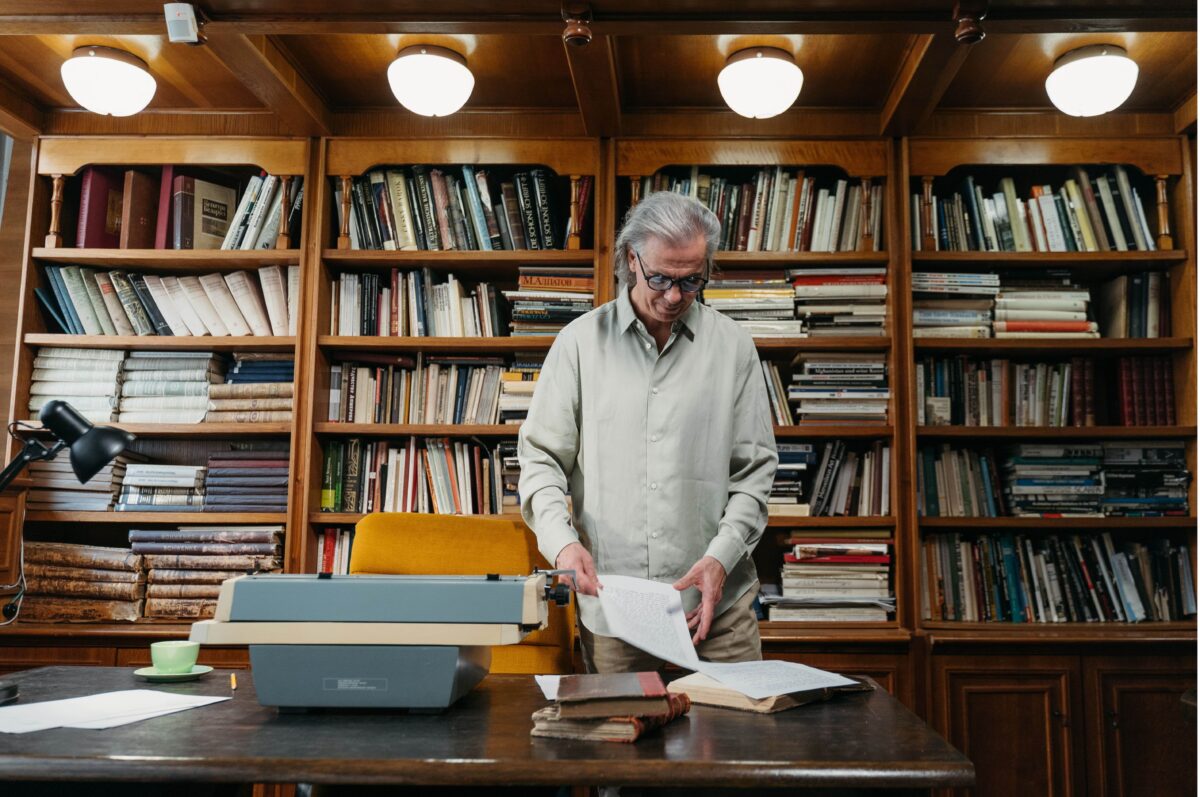Tampaknya mudah untuk bersepakat bahwa saat ini semakin sulit mencari intelektual publik yang istikamah.
Surat edaran internal di Universitas Islam Indonesia terkait peniadaan penulisan jabatan dan gelar rektor dalam dokumen tiba-tiba menjadi viral.
Kejadian di luar dugaan ini merupakan berkah tersamar yang perlu disyukuri. Apa pasal? Ikhtiar kecil tersebut oleh banyak kalangan, termasuk warganet, dianggap sebagai antitesis dari praktik obral gelar dan jabatan kehormatan oleh beberapa kampus. Praktik ini tak jarang melibatkan pejabat dan politisi dengan alasan yang sulit dipahami dengan akal sehat.
Menurut kabar termutakhir, pengajuan untuk mendapatkan jabatan akademik profesor diduga melibatkan praktik suap dengan nominal yang cukup fantastis. Praktik tersebut tentu sangat memalukan di tengah harapan tinggi publik kepada kampus sebagai pengawal moral bangsa.
Surat edaran di atas tentu bukan sekadar instrumen administratif sebagaimana dipahami oleh sebagian orang.
Ada beragam alasan yang lebih substantif meski sudah dapat diduga perspektif ini tidak akan diamini oleh semua profesor. Perbedaan pendapat seperti ini merupakan hal yang sangat wajar di alam demokrasi selama didasari dengan nilai yang baik.
Apa alasan substantif di balik penerbitan surat edaran tersebut? Paling tidak adalah tiga, yakni menumbuhkan kembali semangat kolegialitas, memandang jabatan profesor sebagai amanah publik, dan mendesakralisasi jabatan profesor.
Semangat kolegialitas
Semangat kolegialitas ini sudah agak lama terkikis di tengah maraknya praktik neoliberalisme dalam manajemen perguruan tinggi. Salah satu indikasinya adalah kuasa pasar yang menentukan banyak pilihan sikap. Hubungan internal yang dibangun pun melahirkan jarak kuasa yang semakin jauh, antar-jenjang fungsional dan struktural.
Jabatan profesor yang menghuni jenjang fungsional tertinggi akan menambah jarak sosial dalam berinteraksi. Ujungnya adalah budaya feodalisme gaya baru yang mewujud dalam beragam bentuk di lapangan.
Dengan menghidupkan kembali semangat kolegialitas, jarak kuasa sesama kolega akan semakin dekat.
Kampus akhirnya dapat menjadi salah satu tempat yang paling demokratis. Para dosen menempatkan diri sebagai kolega intelektual yang mempunyai kedaulatan dalam berpikir dan menyatakan pendapatnya.
Peraturan perlu kembali ditata dengan menyuntikkan nilai yang tepat dan menjauhkannya dari kepentingan politik sesaat.
Tanggung jawab publik
Betul, profesor adalah sebuah capaian jabatan akademik tertinggi. Namun, banyak yang lupa bahwa di dalam jabatan itu melekat tanggung jawab publik. Pemahaman ini perlu dilantangkan kembali agar menjadi kesadaran kolektif.
Tanggung jawab publik tersebut dapat termanifestasikan ke dalam beragam peran. Salah satunya adalah intelektual publik. Intelektual tidak boleh menjauh dari urusan publik.
Tugasnya, meminjam formulasi Chomsky (2017), adalah menyampaikan kebenaran dan membongkar kebohongan, memberikan konteks kesejarahan, serta mengungkap tabir ideologi dari beragam gagasan yang mengekang perdebatan publik.
Intelektual publik berikhtiar mendekatkan bidang kajiannya dengan kepentingan publik, termasuk juga bersuara terhadap beragam penyelewengan yang muncul. Menurut Chomsky, karena para intelektual ini mempunyai banyak privilese yang dinikmati, tanggung jawabnya pun lebih besar dibandingkan dengan mayoritas awam.
Tampaknya mudah untuk bersepakat bahwa saat ini semakin sulit mencari intelektual publik yang istikamah.
Didorong oleh kegeraman, seorang kawan bahkan berseloroh jika hari-hari ini kita mengalami surplus profesor, tetapi di saat yang sama kekurangan intelektual publik.
Ikhtiar desakralisasi
Saat ini sebagian kalangan memandang jabatan profesor sebagai sesuatu yang sakral. Banyak orang yang menjadikannya sebagai bagian dari status sosial yang perlu dikejar dengan segala cara, lantas dipamerkan ke ruang publik sebagai kebanggaan.
Sebagian banyak diduga menabrak etika. Kalangan non-akademisi, termasuk politisi dan pejabat, pun akhirnya terpincut untuk mendapatkannya.
Karena dianggap sebagai status sosial tinggi, cerita lucu di lapangan pun bermunculan, termasuk kemarahan si empu ketika jabatan tersebut tidak disematkan. Komentar warganet di beragam linimasa media sosial terkait dengan isu profesor abal-abal menambah daftar kelucuan.
Jika jabatan ini dianggap sakral, si empunya seakan menjadi orang suci, yang jika kebablasan akan menjelma menjadi makhluk yang kalis dari kritik dan kesalahan. Tentu bukan ini yang seharusnya terjadi di dunia akademik. Semua kebenaran bersifat nisbi dan terbuka untuk dikritisi.
Tampaknya mudah untuk bersepakat bahwa saat ini semakin sulit mencari intelektual publik yang istikamah.
Jabatan ini, karena itu, perlu didesakralisasi dengan memutus asosiasinya dengan beragam privilese yang menyertainya yang sebagian bersifat absurd. Privilese muncul karena merupakan legitimasi yang bersumber dari otorisasi pihak yang lebih berkuasa dan endorsemen dari sekelilingnya.
Peraturan perlu kembali ditata dengan menyuntikkan nilai yang tepat dan menjauhkannya dari kepentingan politik sesaat. Pada saat yang sama, penghilangan penulisan jabatan dan pemanggilan dalam interaksi keseharian menjadi salah satu ikhtiar kultural untuk desakralisasi.
Dengan demikian, para pengejar jabatan ini akan diberikan koridor yang bermartabat. Jika mendapatkannya pun si empunya hanya akan merayakan seperlunya dengan penuh kesadaran adanya tanggung jawab publik yang melekat di dalamnya.
Jika kesadaran ini diikuti oleh semakin banyak profesor, tidaklah berlebihan untuk berharap jika gerakan simbolik dalam surat edaran tersebut akan semakin melantang dan melahirkan budaya akademik baru yang lebih egaliter. Semoga.
Tulisan ini dimuat di rubrik Opini Kompas pada tanggal 25 Juli 2024
Fathul Wahid
Ketua Umum Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia (BKS PTIS); Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah Yogyakarta; Rektor Universitas Islam Indonesia. Dosen Jurusan Informatika UII. Bidang riset pada eGovernment, eParticipation, ICT4D, sistem enterprise.