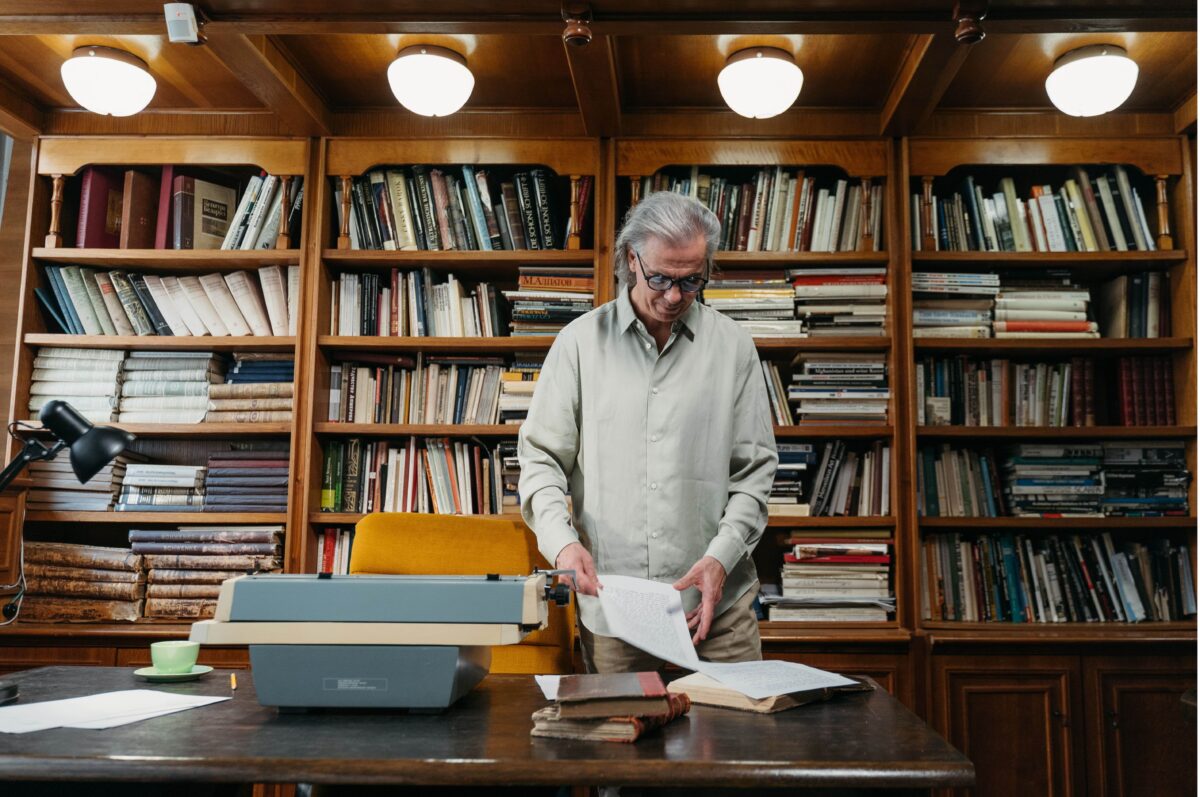Pemberlakuan Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 1 Tahun 2023 untuk memusatkan dan menyederhanakan pengelolaan jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN), menuai sorotan publik–terutama kalangan dosen.
Di antara berbagai pro dan kontra yang terjadi akibat aturan ini, muncul satu perdebatan menarik terkait status ketenagakerjaan dosen di Indonesia.
Sebagian pihak mengkhawatirkan dosen yang kini berfokus menjalankan tugas administratif. Bahkan, belum lama ini dosen sempat dibuat kalang kabut menyelesaikan penyesuaian angka kredit untuk memenuhi aturan baru ini–di tengah segudang beban administratif lain yang sebelumnya sudah menjadi kewajiban mereka.
Dengan kata lain, usaha meneguhkan dosen sebagai “manusia birokrasi” dianggap langkah yang salah karena seolah menempatkan mereka sebagai buruh.
Melalui artikel ini, kami ingin mengajak komunitas akademik untuk berefleksi: Benarkah dosen bukan buruh? Apakah tepat jika kita geram apabila pengelolaan kampus disamakan dengan lembaga politik atau korporasi? Bagaimana komunitas akademik perlu menyikapinya?
Dosen: buruh atau bukan?
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan pekerja/buruh sebagai “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.
Aturan ketenagakerjaan di Indonesia menjamin perlindungan pekerja/buruh. Dalam istilah hukum ketenagakerjaan, hal ini kerap kita sebut “socialisering process” (vermaatschappelijking). Istilah ini adalah serapan dari bahasa Belanda yang merujuk pada campur tangan pemerintah dalam relasi kerja demi melindungi pekerja/buruh.
Di sini, pekerja/buruh adalah pihak yang dianggap lemah dalam hubungan kerja–pola relasinya terbentuk berdasarkan perjanjian kerja. Perjanjian kerja memberikan kewenangan (kuasa) pada pemberi kerja dalam bentuk perintah, sehingga membuat kedudukan kedua pihak menjadi tidak seimbang.
Apakah dosen memenuhi gambaran di atas?
Berdasarkan relasi kerja mereka dengan institusi pendidikan tempat mereka bernaung (pemberi kerja), jawabannya jelas: iya.
Pertama, dosen bekerja pada sebuah perguruan tinggi dan memiliki kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh institusi. Dosen juga memperoleh hak menerima upah atas pekerjaan yang telah ditunaikan. Hak dan kewajiban ini dituangkan dalam perjanjian kerja yang mendasari hubungan antara institusi pendidikan sebagai pemberi kerja dan dosen sebagai pekerja/buruh.
Dosen wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni mengajar, meneliti, dan mengabdi pada masyarakat. Tiga hal ini merupakan indikator kinerja atau prestasi dalam sebuah perjanjian kerja yang wajib mereka tunaikan.
Hal ini sama halnya dengan pekerja/buruh lainnya di sektor formal yang berkewajiban bekerja di bidang masing-masing sesuai yang tercantum dalam perjanjian kerja.
Keduanya berada di posisi yang sama: melaksanakan prestasi, mendapatkan kontraprestasi, dan berhak atas perlindungan yang sama dari regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.
Kedua, status dosen sebagai buruh/pekerja juga terlihat dari mekanisme penyelesaian apabila dosen mengalami perselisihan ketenagakerjaan.
Perjanjian kerja memuat tiga unsur: pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam praktiknya, masalah upah–termasuk yang dialami dosen–paling banyak muncul dan diselesaikan dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
Masalah upah yang bisa saja terjadi, misalnya, ketika institusi pendidikan tidak membayarkan upah kepada dosen.
Hal itu menunjukkan pengakuan secara hukum bahwa perikatan antara institusi pendidikan dan dosen adalah suatu hubungan kerja, antara pemberi kerja dan buruh/pekerja. Perikatan ini berhak dilindungi oleh regulasi ketenagakerjaan Indonesia.
Minim kesadaran kolektif
Sayangnya, kesadaran kolektif mengenai definisi buruh di Indonesia masih terbatas dan diwarnai stereotip. Buruh sering dikaitkan dengan pekerja kerah biru yang pekerjaannya terkait “tenaga jasmani”, seputar “pertukangan”, maupun “buruh pabrik”.
Padahal, apapun profesi dan sektor industrinya, sejauh terdapat hubungan relasi kuasa antara pemilik modal dan pekerja, maka secara substansi pekerja tersebut adalah buruh.
Kesalahpahaman inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa literasi masyarakat mengenai buruh di Indonesia masih sangat terbatas. Dalam peringatan Hari Buruh, kebanyakan demonstrasi yang muncul sepi dari suara pekerja kerah putih dan jauh dari perhatian kebanyakan akademisi Indonesia.
Penempatan dosen sebagai bagian dari kelompok buruh penting untuk mengadvokasi dan meluruskan berbagai norma dalam regulasi pemerintah yang masih belum secara tegas melindungi dan berpihak pada kesejahteraan dosen.
Dosen, kampus, dan transformasi struktural
Pendekatan pemerintah Indonesia dalam pengembangan mutu dan sumber daya pendidikan tinggi sudah sewajarnya mendapatkan umpan balik dari seluruh pemangku kepentingan. Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023, misalnya, dianggap berpotensi menambah kompleksitas birokrasi dan memperkeruh kepastian karier dosen, sehingga patut dikritik.
Namun, kritik tersebut tak semestinya melenceng sampai menganggap bahwa penyamaan dosen sebagai buruh sama dengan merendahkan martabat mereka.
Misalnya, apakah betul dosen memiliki karakteristik profesi yang lebih mulia dibanding pekerja pada umumnya?
Pembedaan status kampus sebagai lembaga khusus yang berbeda dibanding korporasi, jika tidak cermat dalam memahaminya, justru dapat menjebak kampus dalam menara gading yang abai dengan perubahan sosial.
Birokratisasi kampus yang terjadi saat ini, selain merupakan warisan era penjajahan, sebenarnya lebih tepat kita lihat sebagai dampak atas transformasi struktural di tingkat global yang membuat kampus bergerak dengan logika kompetisi ala korporasi dan mengejar predikat kelas dunia.
Transformasi itu dimulai sejak munculnya perubahan paradigma dalam memahami peran perguruan tinggi seiring globalisasi ekonomi yang terjadi pada dekade 1960-an.
Sebelumnya, kampus dianggap sebagai aktor utama yang berperan mengembangkan pengetahuan. Riset cenderung berbasis pengabdian sosial dan lebih banyak didorong oleh semangat kebaruan ilmu pengetahuan.
Kini, dunia terjerat dalam sistem kapitalisme neoliberal–yang menekankan kompetisi pasar bebas dan transfer wewenang dari sektor publik ke sektor swasta dalam mengendalikan perekonomian. Akibatnya, eksistensi kampus ikut terseret ke dalam perangkap mekanisme pasar.
Kampus berubah menjadi korporasi pengetahuan dan membuat mutu riset lebih banyak diukur dari keberhasilan komersialisasi dan publikasi berbasis angka.
Kriteria mutu staf akademik juga berubah: dari kinerja yang berfokus pada pengajaran atau riset, ke kriteria profesionalisme akademik yang lebih universal dan komersial.
Universalisasi, misalnya, terlihat dari bagaimana indeksasi jurnal – seperti Scopus – mendikte persepsi mengenai mutu artikel ilmiah. Sementara, komersialisasi membuat akademisi dipacu untuk berkontribusi terhadap inovasi negara melalui paten. Semakin banyak jumlah paten, peringkat universitas di tataran global pun semakin terdongkrak.
Dampaknya, kampus menjadi kian hierarkis–layaknya tangga korporasi–sehingga menghilangkan semangat kolegialitas (menekankan solidaritas sesama pengajar). Dosen juga menghadapi beban birokrasi yang masif.
Ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Riset menunjukkan bahwa birokratisasi kampus sebenarnya adalah tren global yang tengah terjadi di berbagai negara, termasuk di kawasan Eropa dan Australia. Kampus menjadi lembaga yang semakin birokratis, tidak lagi kolegial dalam proses pembuatan kebijakan.
Transformasi struktural ini juga berhasil mengubah model sistem penghargaan akademik dari kedalaman kepakaran dosen menjadi prestasi dosen berbasis metrik.
Pemeringkatan kampus dunia menjadi puncak komersialisasi kampus. Mutu dan peringkat pendidikan tinggi akhirnya sekadar berkiblat pada model-model perguruan tinggi di negara maju.
Saat kampus terjerat mekanisme pasar, peran dosen menjadi semakin kering. Fungsi dosen sebagai pembentuk karakter generasi tidak lagi diukur. Demi peringkat, dosen dipaksa produktif menghasilkan publikasi “bereputasi”–bahkan terkadang membuat mereka melakukan praktik buruk dan mengambil jalan pintas.
Desain ketenagakerjaan dosen semakin dibatasi dengan aturan karier dan performa kinerja yang semakin berbasis metrik, administratif, dan menjauhi substansi akademik.
Sebagai buruh, dosen perlu lebih awas terhadap isu ketenagakerjaan yang timbul akibat dinamika di atas.
Birokrasi memang punya sejumlah manfaat, tapi dosen juga tetap harus kritis mengawalnya agar efisien. Pasalnya, banyak perguruan tinggi yang menerapkan berbagai kewajiban administrasi sehingga mengganggu tanggung jawab utama dosen, yakni aktivitas akademik dan riset.
Untuk mengawal hal-hal ini, sekaligus melindungi nasib dosen secara kolektif, serikat pekerja kampus di Indonesia perlu kita tumbuhkan. Di dalamnya bisa termasuk serikat dosen dan tenaga kependidikan. Semakin banyak serikat pekerja kampus, semakin bagus.
Selama ini organisasi dosen lebih didorong oleh kesamaan rumpun ilmu dan minat pengembangan akademik. Kini, tiba waktunya warga kampus membangun kanal negosiasi kolektif dengan berserikat guna melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Tulisan sudah dimuat di The Conversation Indonesia pada tanggal 01 Mei 2023
Hangga Fathana
Dosen Jurusan Hubungan Internasional UII. Bidang riset pada studi Australia, politik ekonomi global, politik perdagangan, dan dinamika perkembangan kapitalisme.