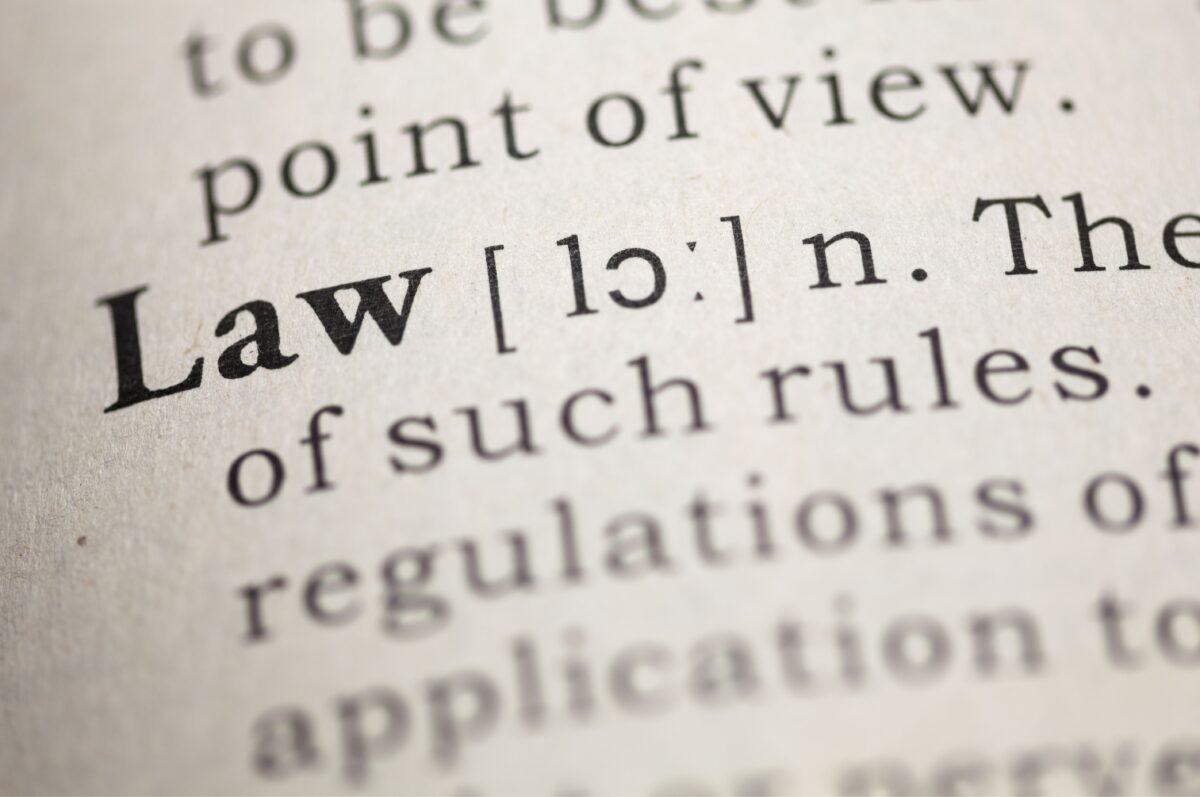Pada 25 Mei 2023 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi 5 tahun , dari yang sebelumnya 4 tahun. Pemohon dalam uji materi ini adalah Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK periode saat ini.
Menurut putusannya, terdapat dua alasan mengapa MK mengabulkan permohonan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.
Pertama adalah adanya perlakuan diskriminatif dan tidak adil terhadap KPK apabila menyamakannya dengan lembaga pemerintah independen lainnya yang sama-sama memiliki constitutional importance, yakni memiliki masa jabatan 5 tahun. Kedua adalah karena berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan KPK selama 5 tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien sehingga dapat sesuai dengan satu periode jabatan presiden.
Putusan MK tersebut langsung menjadi sorotan dari berbagai pihak. Banyak elemen yang menyayangkan putusan MK ini karena berdekatan dengan momentum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sehingga dinilai sarat dengan kepentingan politik.
Kekecewaan publik terhadap Putusan MK bisa dipahami, karena Ketua KPK periode 2019-2023, Firli Bahuri, kerap berhadapan dengan masalah kode etik. Namun, ia selalu lolos dari sanksi berat Dewan Pengawas KPK. Terlebih lagi, suara 9 hakim MK pun terpecah untuk putusan MK. Sebanyak 4 hakim MK menolak (dissenting opinion) perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK ini.
Meskipun putusan MK sudah tidak dapat diganggu gugat (final and binding), paling tidak ada beberapa kritik yang dapat kita sampaikan sebagai publik, sebagai sarana edukasi agar kita bisa lebih ketat dan kritis dalam mengawal kinerja MK.
Kritik terhadap putusan MK
Pertama, MK bukan lembaga negara sepenuhnya demokratis karena tidak dipilih langsung oleh rakyat, sementara masa jabatan sangat berkaitan erat dengan domain perumusan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy).
Dengan kata lain, perpanjangan masa jabatan pimpinan lembaga manapun seharusnya dilakukan melalui lembaga pembuat undang-undang, yakni lembaga legislatif, yang secara resmi didaulat sebagai wakil rakyat dan di dalamnya memiliki proses partisipasi publik.
Kedua, dalil perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang diterima oleh pimpinan KPK sebenarnya bisa terbantahkan dengan adanya ketidakseragaman masa jabatan sejumlah lembaga negara, seperti pimpinan Komisi Informasi (4 tahun) dan pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (3 tahun).
Terlebih lagi, definisi perlakuan diskriminatif memiliki kriteria khusus. Ini termasuk pembedaan berdasar atas alasan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Kriteria tersebut secara faktual tidak terjadi pada pimpinan KPK.
Ketiga, jika memang masa jabatan pimpinan KPK perlu diperpanjang demi efektivitas kinerja mereka, ketentuan ini lebih baik diberlakukan untuk periode selanjutnya, bukan kepada pimpinan KPK aktif yang saat ini masih menjabat. Putusan seperti ini seharusnya menerapkan asas non-retroaktif yang bersifat universal, yakni ketika suatu aturan hukum tidak dapat berlaku surut.
Keempat, mengubah masa jabatan pejabat aktif jelas akan mengancam independensi lembaga negara terkait, dan ini bisa menjadi preseden buruk di kemudian hari. Apalagi ini terjadi pada lembaga antirasuah, lembaga yang telah bertahun-tahun menjadi salah satu lembaga yang paling dipercaya publik berdasarkan hampir semua hasil survei.
Ke depannya, dikhawatirkan MK sewaktu-waktu bisa saja mengubah masa jabatan pimpinan lembaga negara yang sedang menjalankan tugasnya atas dasar kepentingan dan motif politik tertentu.
Kita semua percaya bahwa MK masih kokoh berdiri sebagai lembaga independen yang menjadi garda terdepan dalam mengawal konstitusi kita. Namun, jika demi kepentingan politik, apalagi menjelang tahun politik, segala sesuatunya bisa terjadi, sehingga tidak salah jika publik lebih waspada.
Praktik perpanjangan masa jabatan pimpinan lembaga negara
Praktik perpanjangan masa jabatan pimpinan lembaga negara kerap kali menjadi jurus andalan bagi penyelenggara negara guna seseorang untuk duduk di kursi kekuasaan lebih lama.
Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, setidaknya ada 3 kali upaya untuk mengubah masa jabatan lembaga negara, termasuk MK sendiri, KPK, dan lembaga kepresidenan , meskipun perpanjangan gagal diterapkan pada lembaga kepresidenan.
Perpanjangan masa jabatan hakim pada MK yang sedang aktif menjabat dilakukan pada 2020, dengan cara mengubah UU tentang Mahkamah Konstitusi. Masa jabatan periodik hakim MK yang sebelumnya hanya 5 tahunan diubah dengan penentuan usia pensiun 70 tahun dengan keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun.
Pada awal tahun 2022, para petinggi partai politik sempat menggaungkan gagasan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024. Elemen masyarakat sipil ramai-ramai menolak wacana tersebut karena diyakini akan membuka ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
Perubahan masa jabatan presiden memang sulit diwujudkan karena harus melalui amendemen UUD 1945. Namun, sekali lagi, menjelang tahun politik, apa pun bisa terjadi.
Praktik perpanjangan masa jabatan hampir selalu dilakukan dengan balutan hukum, padahal sebenarnya telah merusak independensi dan mengikis demokrasi. Hal seperti ini banyak ditemui di negara-negara dengan rezim legalisme otokratis (autocratic legalism), yaitu kondisi ketika kekuasaan suatu negara hanya dipegang oleh satu atau segelintir orang saja dan hukum disalahgunakan untuk melegitimasinya, seperti Turki dan Venezuela.
Jalan tengah
Kita tidak boleh terjebak menjadi rezim semacam itu. Pada kasus perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK ini, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pembuat UU bersepakat untuk menindaklanjuti putusan MK dengan memberlakukannya pada pimpinan KPK yang berikutnya.
Cara ini dilakukan agar, di satu sisi, pemerintah dan DPR tetap menghormati Putusan MK yang bersifat final dan mengikat, tetapi di sisi lain juga untuk melindungi independensi lembaga negara penegak hukum.
Dalam hal ini, Presiden perlu mengambil peran penting untuk menyelesaikan polemik ini dan menjamin bahwa independensi lembaga negara tidak dapat diganggu dengan cara apa pun. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang tunduk pada konstitusi juga memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan harapan bahwa reformasi hukum ketatanegaraan terus bergerak ke arah yang lebih baik.
Tulisan sudah dimuat di The Conversation Indonesia pada tanggal 17 Juni 2023
M. Addi Fauzani
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII.