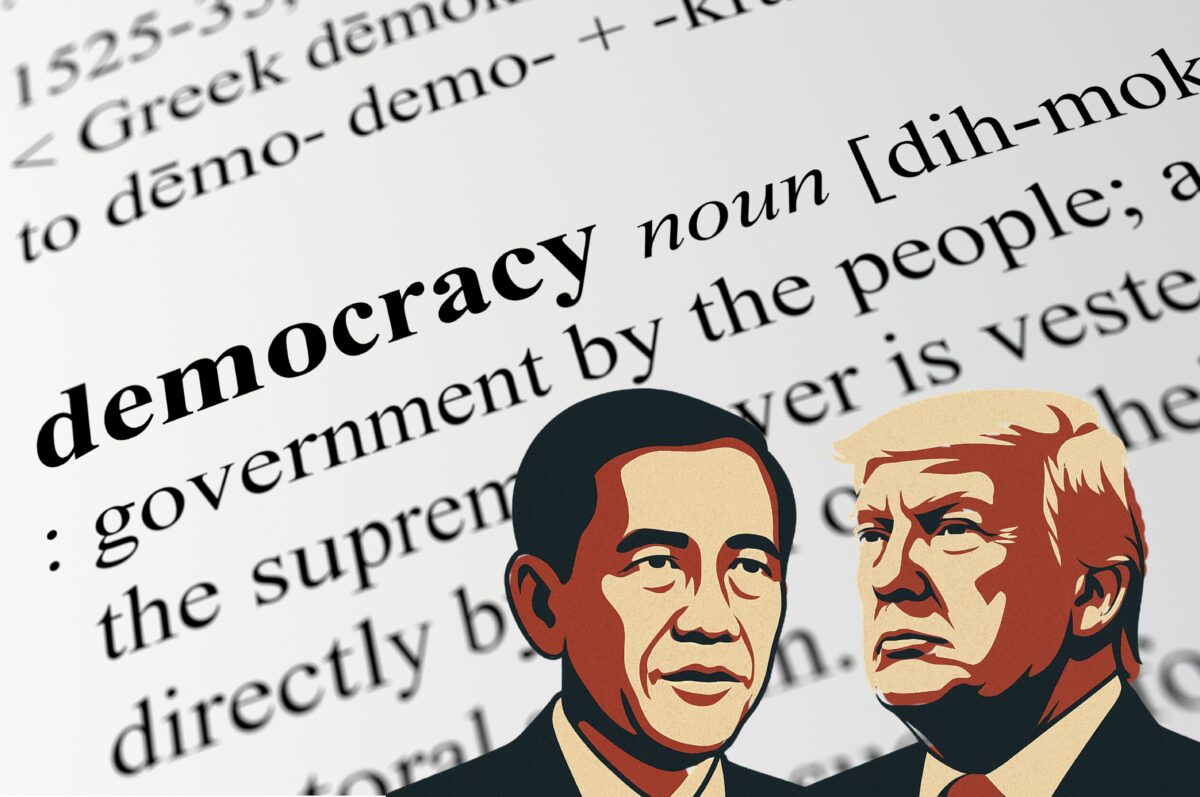Kita pernah mencoba dalam waktu yang sangat panjang mengelola hubungan pusat dan daerah dengan prinsip sentralisasi yang hasilnya ketimpangan dan ketidakadilan.
Apa yang terjadi belakangan ini mengenyak kesadaran tentang masa depan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia. Diawali dengan retret semua kepala daerah terpilih di markas Akademi Militer Magelang. Presiden, melalui Menteri Dalam Negeri, mewajibkan semua kepala daerah untuk mengikuti retret. Wajib dalam frasa hukum mengandung makna sanksi bagi siapa saja yang tidak mengikutinya tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
Dilanjutkan dengan pernyataan Mendagri bahwa ”Presiden adalah pimpinan eksekutif tertinggi sehingga kepala daerah adalah bawahannya yang harus tunduk pada kehendak Presiden”. Realitas dan pernyataan pemerintah pusat di atas menandai tonggak awal masa depan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia yaitu kelam!
Bangunan otonomi daerah
Hingga tahun 2014, isu otonomi daerah adalah isu yang menarik dibicarakan. Kita sedang mencari dengan serius tentang bagaimana kewenangan serta kekuasaan pusat dan daerah akan ditata, dikelola, dan dibangun.
Jika ditarik ke belakang, salah satu isu besar reformasi dan amendemen UUD 1945 adalah penataan hubungan pusat dan daerah, yang disulut oleh realitas ketidakadilan hingga ketimpangan pusat dan daerah. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan kewenangan kepada derah untuk mengurus urusannya dengan mandiri dan otonom, inilah yang dimaknai dengan asas desentralisasi sebagai lawan dari sentralisasi.
Lihatlah bagaimana pengaturan hubungan pusat dan daerah dalam konstitusi pasca-amendemen. Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD N RI Tahun 1945 berbunyi, ”Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” serta ”Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.
Prinsip otonomi seluas-luasnya, menurut Bagir Manan, adalah prinsip dengan pemerintah daerah menjalankan kewenangan residu, artinya seluruh kewenangan pada dasarnya adalah milik pemerintah daerah, kecuali yang ditentukan menjadi urusan/kewenangan pemerintah pusat.
Tentang bagaimana sumber daya dikelola, Pasal 18A menyatakan, ”Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”
Senja kala otonomi daerah
Sayangnya, apa yang dirumuskan dan diangankan dalam konstitusi pasca-amendemen hari ini jauh panggang dari api. Dalam catatan penulis, isu mengenai otonomi daerah mulai ditinggalkan dan dilupakan dari diskusi publik adalah sejak 2014, masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Arah kebijakan pemerintahan ketika itu adalah menarik kembali kewenangan yang sebelumnya diberikan kepada pemerintah daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah mantra yang manjur untuk menarik kembali berbagai kewenangan itu hingga tidak ada yang tersisa bagi daerah.
Belakangan, munculnya UU Cipta Kerja membabat habis kewenangan daerah, hanya menyisakan apa yang diberikan oleh pemerintah pusat saja, yang itu sangatlah sedikit. Logika stabilitas politik, peningkatan ekonomi, dan pembangunan adalah yang selama ini digaungkan. Otonomi daerah dianggap menjadi momok bagi kebijakan pemerintah pusat sehingga harus dihapuskan.
Masa awal pemerintahan Prabowo sudah menunjukkan ketidakberpihakan terhadap otonomi daerah. Menempatkan militer dan polisi aktif menduduki jabatan publik, pada dasarnya bertolak belakang dengan prinsip otonomi daerah karena logika otonomi daerah adalah kemandirian dan kebebasan. Berbeda dengan logika militer yang justru mengedepankan satu komando dan hierarki.
Lalu, retret yang dijalani oleh semua kepala daerah di Magelang juga patut dibaca sebagai kondisi prinsip otonomi daerah semakin lemah. Pemerintah pusat ingin agar daerah menggunakan cara kerja militer, yang meniadakan kebebasan dan kemandirian daerah untuk mengurus urusan berdasarkan prinsip otonomi.
Ini diperburuk dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri, yang secara khusus membidangi otonomi daerah, bahwa Kepala Daerah adalah bawahan Presiden sebagai pimpinan eksekutif tertinggi. Pernyataan ini bukan saja ahistoris, tetapi juga lemah argumentasi konstitusional.
Presiden dan Kepala Daerah adalah sama-sama pimpinan eksekutif, keduanya memiliki legitimasi yang sama karena dipilih langsung oleh rakyat, bedanya terletak pada level teritori atau cakupan wilayahnya saja. Keduanya juga menjalankan kewenangan berdasarkan atribusi UU sehingga tidak ada yang lebih rendah dari yang lain. Begitulah logika hubungan pusat dan daerah jika dibaca dengan cermat dalam Pasal 18, 18A, dan 18B UUD N RI Tahun 1945.
Ada dua hal yang harus dipertimbangkan kembali oleh Presiden Prabowo dalam melihat hubungan pusat dan daerah yang hari ini eksis. Pertama, UUD NRI Tahun 1945 menghendaki agar daerah memiliki otonomi yang luas dengan prinsip kemandirian dan kebebasan. Sebagai presiden yang disumpah untuk menaati konstitusi, Presiden Prabowo tahu persis bagaimana menempatkan UUD.
Kedua, kita pernah mencoba dalam waktu yang sangat panjang, Orde Lama dan Orde Baru, mengelola hubungan pusat dan daerah dengan prinsip sentralisasi seperti saat ini, tapi yang dihasilkan adalah ketimpangan dan ketidakadilan. Bahkan, berujung pada gerakan separatisme beberapa daerah karena menuntut keadilan. Artinya, cara itu selalu menemui jalan buntu, maka tidak selayaknya dilanjutkan.
Tulisan sudah dimuat di rubrik Opini Kompas pada tanggal 29 April 2025
Despan Heryansyah
Dosen Fakultas Hukum UII dan Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK). Bidang riset pada hak asasi manusia dan kebijakan publik, hak-hak kelompok rentan, dan pemerintahan daerah.