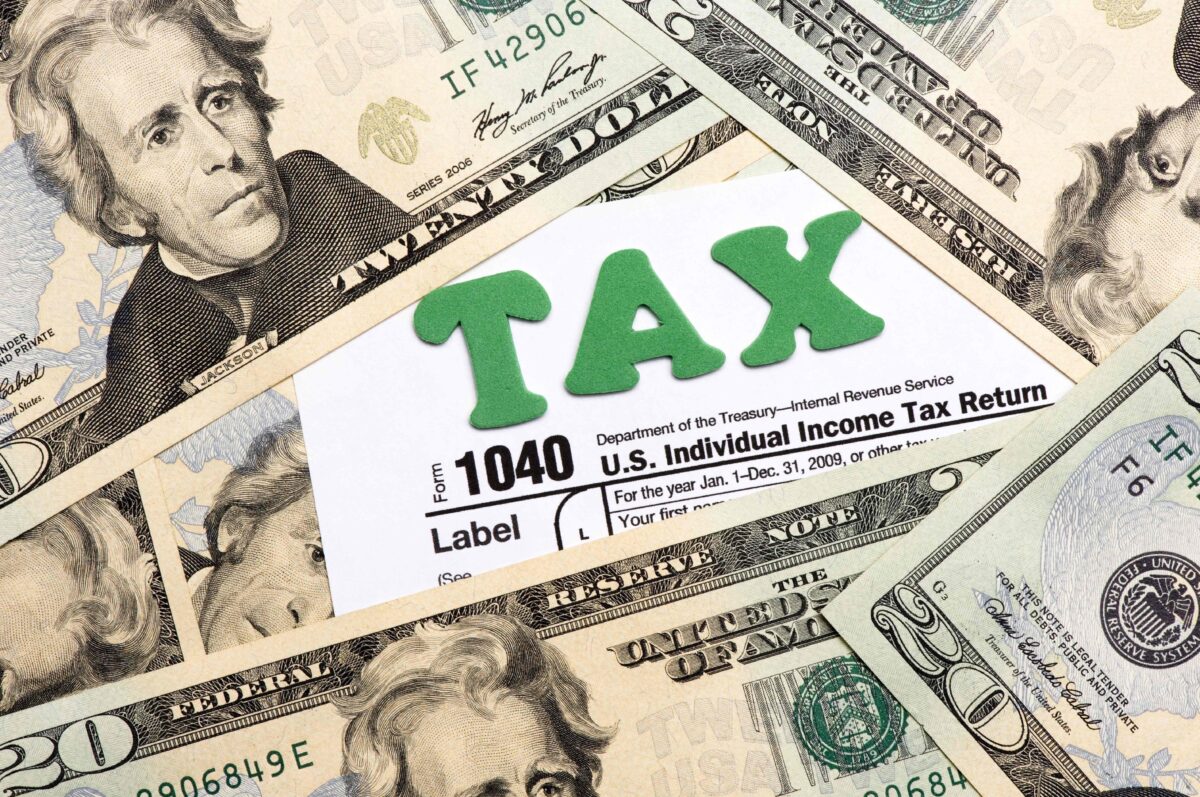Meski kebutuhan pokok seperti sembako sebagian besar dikecualikan, barang-barang sekunder yang juga krusial bagi konsumsi rumah tangga akan terkena imbasnya.
Mampukah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen menjadi penggerak ekonomi melalui optimalisasi pendapatan negara, atau justru akan menjadi pengerem ekonomi yang melemahkan daya beli dan sektor riil?
Pemerintah berdalih, langkah menaikkan tarif PPN diperlukan guna meningkatkan penerimaan negara demi pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Namun, bagi masyarakat kecil, kebijakan ini menyulut kekhawatiran baru. Harga barang dan jasa yang kian melonjak menjadi beban berat, terutama di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Keputusan pemerintah untuk meningkatkan tarif PPN bukanlah langkah yang diambil tanpa dasar. Sejak awal diterapkannya sistem PPN di Indonesia pada 1984, kebijakan ini dirancang sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara. Dalam beberapa dekade terakhir, PPN menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas fiskal.
Ketika defisit anggaran meningkat, seperti yang terjadi selama pandemi Covid-19, pemerintah berupaya mencari cara untuk menutup celah pendanaan tanpa terlalu membebani kelompok berpenghasilan rendah.
Pilihan untuk menaikkan PPN, dibandingkan pajak lainnya, karena PPN dianggap memiliki basis yang lebih luas dan efisien dalam pengumpulan.
Namun, sejarah juga mencatat, setiap kali terjadi kenaikan tarif PPN, respons masyarakat tak pernah sederhana.
Pada tahun 2001, ketika tarif PPN naik dari 10 persen menjadi 11 persen, terjadi peningkatan inflasi sebesar 1,2 persen yang langsung memukul daya beli masyarakat. Situasi serupa terjadi pada 2022 ketika PPN dinaikkan dari 10 persen menjadi 11 persen, dengan lonjakan inflasi mencapai 4,2 persen.
Dengan memahami histori ini, kita dapat melihat mengapa pemerintah memilih kebijakan ini meski menyadari potensi risiko ekonomi yang menyertai.
Dampak dari kebijakan ini dapat dilihat dari berbagai perspektif. Dalam konteks pemulihan ekonomi nasional, pendapatan pajak yang meningkat diyakini mampu mendukung program-program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Namun, pada saat yang sama, daya beli masyarakat yang rendah akibat kenaikan harga dapat menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi lokal. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi tahunan pada 2024 diproyeksikan berada di kisaran 4-5 persen, sebagian besar dipicu oleh kenaikan harga barang dan jasa yang dikenai PPN. Dengan basis data ini, penting untuk menganalisis lebih dalam dampak dan potensi dari kebijakan kenaikan tarif PPN.
Perspektif pemerintah
Pemerintah mengklaim meningkatkan tarif PPN adalah langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal negara. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah dapat melanjutkan program prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan.
Pada tahun 2023, pendapatan pajak Indonesia mencapai Rp 1.716 triliun, di mana PPN menyumbang sekitar 38 persen dari total pendapatan tersebut. Dengan peningkatan tarif menjadi 12 persen, pemerintah memproyeksikan tambahan penerimaan hingga Rp 150 triliun per tahun, yang dapat dialokasikan untuk berbagai program pembangunan.
Selain itu, pemerintah menekankan bahwa tarif 12 persen masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN seperti Filipina dan Vietnam yang mengenakan PPN hingga 15 persen. Klaim ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam batas wajar secara regional.
Namun, klaim ini perlu diuji lebih jauh. Apakah dana yang terkumpul benar-benar dikelola secara efisien dan tepat sasaran? Tantangan utama kebijakan fiskal di Indonesia bukan hanya pada aspek penerimaan, melainkan juga pada pengelolaan dan transparansi anggaran.
Pemerintah juga berargumen, kenaikan tarif ini tak serta-merta membebani rakyat kecil karena beberapa barang dan jasa kebutuhan pokok dikecualikan dari PPN. Namun, pertanyaan tetap ada: bagaimana kebijakan ini berdampak pada barang sekunder dan jasa lainnya yang turut memengaruhi konsumsi masyarakat? Dampak jangka pendek seperti penurunan daya beli dan inflasi perlu menjadi perhatian serius untuk memastikan kebijakan ini tidak menghambat pemulihan ekonomi.
Pemerintah mengklaim meningkatkan tarif PPN adalah langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal negara.
Dampak pada ekonomi rakyat
Kenaikan tarif PPN berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian rakyat. Salah satu dampaknya, lonjakan harga barang dan jasa.
Meski kebutuhan pokok seperti sembako sebagian besar dikecualikan, barang-barang sekunder yang juga krusial bagi konsumsi rumah tangga akan terkena imbasnya. Menurut survei BPS di triwulan I-2024, pengeluaran rumah tangga pada barang sekunder mengalami penurunan hingga 12 persen dibandingkan dengan periode sama 2023. Penurunan ini mencerminkan kekhawatiran konsumen akan kenaikan harga akibat PPN.
Efek ini bukan hanya bersifat ekonomi, melainkan juga psikologis, melemahkan daya beli masyarakat yang sudah rentan. Dalam konteks ekonomi mikro, teori permintaan menunjukkan kenaikan harga biasanya menyebabkan penurunan konsumsi, terutama untuk barang yang elastis. Daya beli masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada pada level menengah ke bawah membuat mereka lebih sensitif terhadap perubahan harga.
Bagi sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, dampaknya lebih nyata. UMKM menyumbang sekitar 61 persen produk domestik bruto (PDB) dan mempekerjakan lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional. Tekanan biaya produksi yang meningkat akibat kenaikan tarif PPN bisa mengurangi margin keuntungan mereka.
Di sisi lain, penurunan konsumsi domestik berisiko mengurangi omzet UMKM dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.
Kebijakan ini juga menyoroti sifat regresif dari PPN, di mana beban pajak cenderung lebih berat dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah dibandingkan dengan kelompok kaya. Data OECD menunjukkan bahwa sistem pajak regresif dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi jika tidak diimbangi dengan kebijakan redistributif yang efektif.
Kebijakan penyeimbang
Untuk memastikan kenaikan tarif PPN tidak menimbulkan gejolak yang terlalu besar, diperlukan kebijakan penyeimbang yang komprehensif.
Pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi UMKM untuk meredam dampak kenaikan tarif ini. Sebagai contoh, pembebasan pajak untuk bahan baku tertentu yang digunakan UMKM dapat menjadi solusi untuk menekan biaya produksi. Selain itu, perluasan program bantuan sosial yang tepat sasaran juga menjadi solusi penting untuk menjaga daya beli masyarakat miskin.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk bantuan sosial pada tahun 2024 mencapai Rp 470 triliun, tetapi efektivitas distribusinya masih perlu ditingkatkan.
Pengalaman negara-negara seperti Jerman dan Swedia menunjukkan bahwa tarif PPN yang tinggi bisa diterapkan tanpa menekan ekonomi rakyat, asalkan diimbangi dengan subsidi langsung dan insentif yang memadai. Di Jerman, subsidi untuk energi dan transportasi publik membantu meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak. Tanpa langkah ini, kenaikan tarif PPN hanya akan menambah beban tanpa memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Selain itu, kebijakan untuk meningkatkan literasi pajak di kalangan masyarakat juga penting. Sebagai bagian integral dari ekosistem ekonomi, masyarakat memiliki peran penting dalam menyikapi kebijakan ini. Salah satu langkah awal adalah meningkatkan pemahaman tentang pajak, termasuk tujuan kenaikan tarif PPN dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
Dengan memahami konteks kebijakan, masyarakat bisa mengurangi resistensi yang berbasis pada kesalahpahaman.
Untuk memastikan kenaikan tarif PPN tidak menimbulkan gejolak yang terlalu besar, diperlukan kebijakan penyeimbang yang komprehensif.
Langkah mitigasi
Agar kenaikan tarif PPN menjadi langkah yang konstruktif, pemerintah perlu menyiapkan strategi mitigasi yang komprehensif untuk meredam dampak negatif kebijakan ini, terutama bagi masyarakat kecil dan sektor UMKM.
Pertama, memberikan subsidi langsung untuk barang dan jasa esensial dalam kehidupan masyarakat, seperti transportasi publik, bahan bakar, dan energi rumah tangga, untuk menjaga daya beli masyarakat.
Kedua, memberi insentif pajak bagi UMKM dan sektor riil, berupa pembebasan/pengurangan PPN untuk bahan baku tertentu yang digunakan UMKM dan insentif khusus untuk sektor riil yang terdampak langsung. Ini bisa membantu pelaku usaha menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas operasional.
Ketiga, perluasan dan efisiensi program bansos. Meningkatkan cakupan dan ketepatan sasaran program bansos seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau kartu sembako. Penggunaan data terkini yang akurat sangat penting untuk memastikan bantuan ini sampai kepada yang benar-benar membutuhkan.
Keempat, kebijakan harga yang terjangkau untuk kebutuhan pokok. Mengendalikan harga barang kebutuhan pokok melalui pengawasan rantai distribusi, serta memberikan insentif kepada produsen untuk menjaga stabilitas harga di tengah kenaikan tarif pajak.
Kelima, edukasi dan literasi pajak bagi masyarakat dan pelaku usaha. Keenam, penguatan transparansi dan akuntabilitas dana publik. Ketujuh, peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran. Memastikan setiap tambahan penerimaan negara dari PPN digunakan secara optimal, mengurangi pemborosan, dan memprioritaskan proyek yang memberi dampak sosial-ekonomi terbesar. Kedelapan, monitoring dan evaluasi dampak kebijakan.
Dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi ini, pemerintah tidak hanya dapat meminimalkan dampak negatif kebijakan kenaikan PPN, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan fiskal yang diambil.
Tulisan sudah dimuat di rubrik Opini Kompas pada tanggal 30 Desember 2024
Listya Endang Artiani
Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi UII. Bidang riset pada makroekonomi, ekonomi moneter, dan ekonomi energi