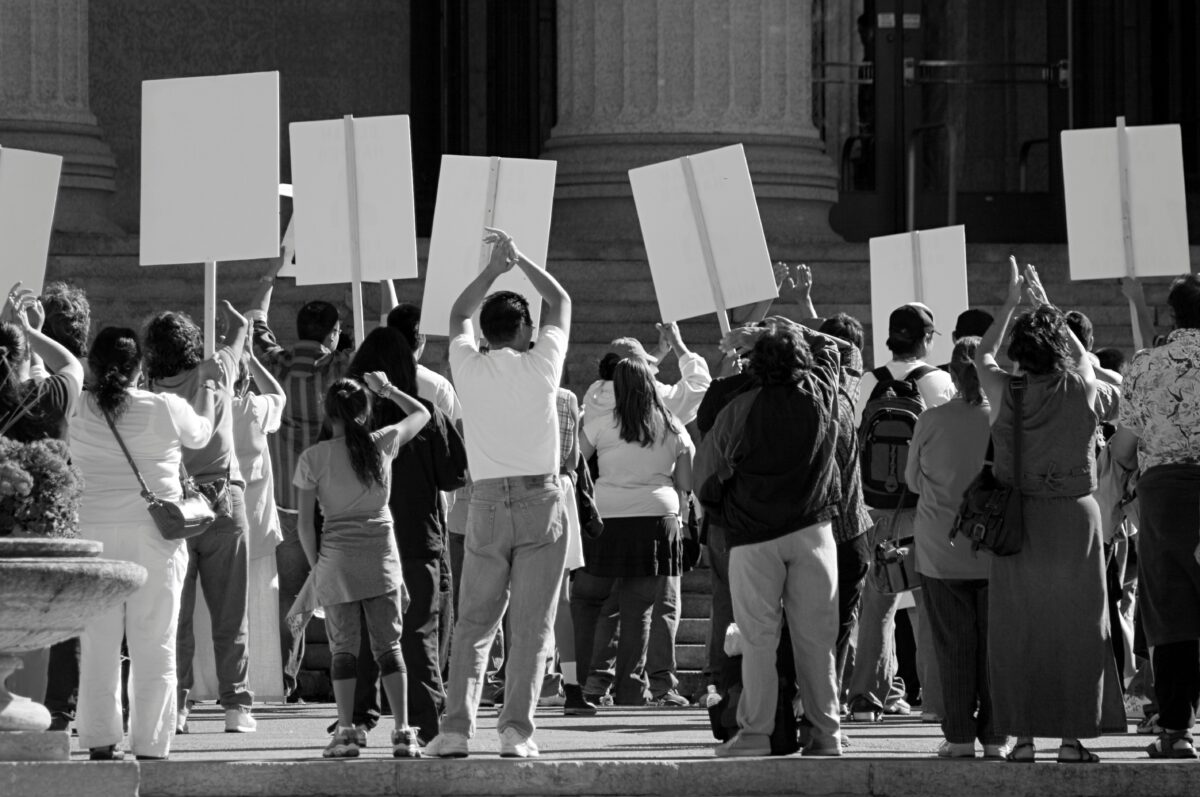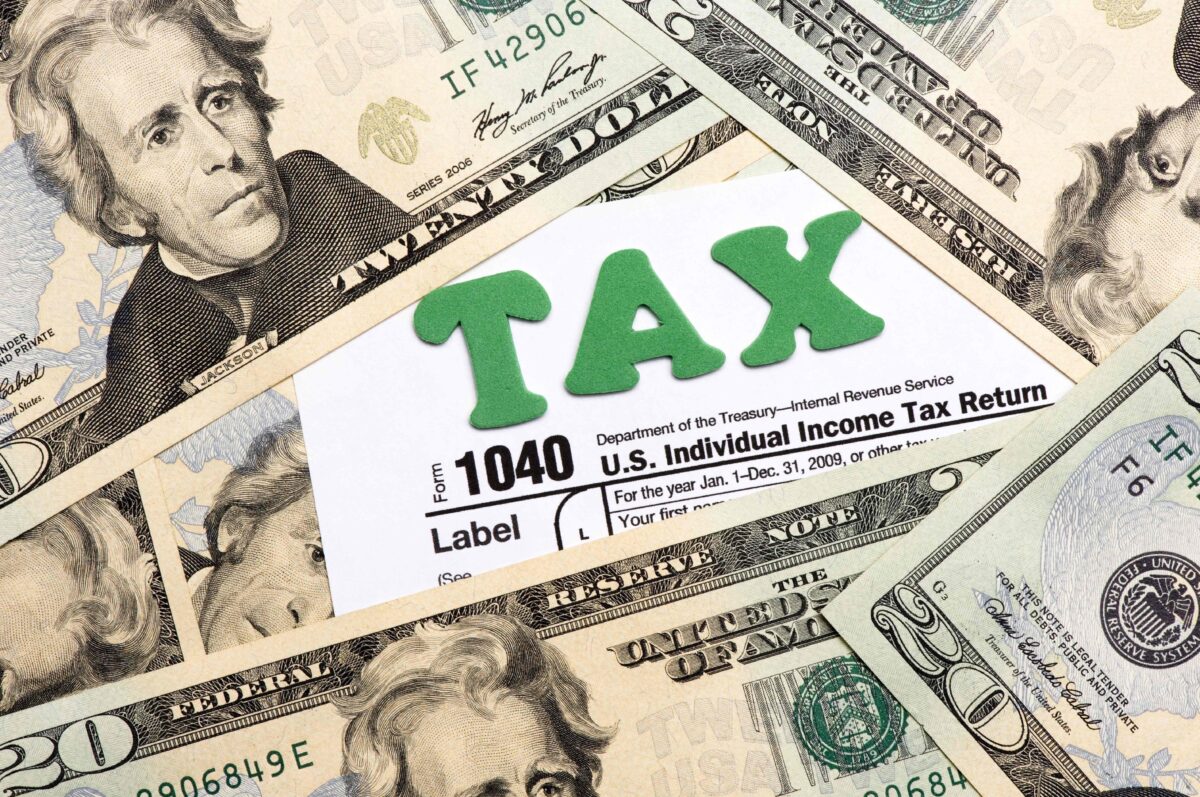Kunjungan apostolik yang dilakukan oleh Paus Fransiskus ke Indonesia memberikan hikmah dan pelajaran yang berlimpah bagi seluruh umat beriman. Dalam pidato dan khotbah yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam ragam forum di Indonesia, ada satu poin utama yang coba ditegaskan oleh Paus dalam setiap penjelasannya, yaitu bagaimana umat beriman di Indonesia dapat memaknai kembali hubungan Allah, alam, dan umat manusia.
Penjelasan yang disampaikan dan solusi yang ditawarkan oleh Paus Fransiskus didasarkan pada filsafat fransiskan yang berangkat dari pemikiran dan laku Santo Fransiskus dari Asisi, seorang rahib dan teolog Katolik pada Abad Pertengahan.
Pemikiran Santo Fransiskus dari Asisi juga tumbuh pada masa-masa krisis setelah kontestasi berdarah antara kuasa muslim dan kristen pada masa itu yang menimbulkan dampak serius terhadap masyarakat sipil.
Hal itulah yang membuat Paus Fransiskus memilih Santo Fransiskus dari Asisi sebagai nama kepausan. Pola pikir fransiskan memberikan takhta suci Vatikan kesempatan untuk memikirkan kembali posisi agama dan takhta suci dalam krisis multidimensional yang tidak mudah pada kurun kedua abad ke-21.
Dasar pemikiran Fransiskan
Terdapat tujuh nilai dasar Fransiskan yang menjadi laku harian para pengikut tarikat fransiskan hingga masa kini dan menginspirasi pola hidup umat Katolik. Pertama, fransiskan sangat mengutamakan penghormatan dan perlindungan terhadap makhluk hidup seperti yang tergambar dalam dalam doa Santo Fransiskus dari Asisi yang menginspirasi ensiklik Laudato St.
Kedua, fransiskan memberikan tempat khusus pada perlindungan terhadap muruah dan harga diri manusia. Ketiga, fransiskan menganggap bahwa setiap manusia harus dijaga kehidupannya terlepas dari latar belakang kehidupan manusia tersebut. Keempat, fransiskan juga memberikan penekanan yang amat besar terhadap kaum miskin dan masyarakat yang memiliki kerentanan secara sosial dan ekonomi.
Fransiskan memiliki teologi kasih yang berpusat pada welas asih dan laku hidup sederhana yang memberikan umat beragama ruang eksplorasi untuk peduli pada sesama.
Kelima, fransiskan dikenal juga dengan aktivismenya dalam isu perdamaian dan rekonsiliasi konflik yang tergambar dalam slogannya Pax et bonum, damai dan kelakuan baik. Dasar dari slogan Pax et bonum itulah yang kemudian menginspirasi Paus Fransiskus untuk merumuskan dokumen bersejarah Deklarasi Persaudaraan Manusia dan ensiklik Fratelli Tutti untuk mendorong pola pikir yang menerobos kejumudan dan konflik yang tak kunjung berakhir.
Keenam, fransiskan juga beranggapan bahwa ada kesejalanan di antara keadilan dan kedamaian yang perlu berjalan secara seiringan untuk mengoreksi kuasa yang dapat berlaku lalim dan tanpa batas sehingga merugikan hidup kaum miskin dan masyarakat rentan.
Ketujuh, fransiskan memberikan peluang untuk transformasi diri yang akan berpe- ngaruh pada transformasi masyarakat se- hingga setiap orang Katolik yang mengikuti teologi Fransiskan diekspektasikan untuk menjadi agen perubahan.
Yunus Emre sebagai sufi rakyat
Dalam perspektif Islam, filsafat fransiskan dapat didialogkan secara berkelanjutan dengan filsafat sufi. Salah satu figur sufi dalam sejarah Islam, Yunus Emre, merupakan seorang tokoh yang memiliki latar belakang yang cukup serupa dengan Santo Fransiskus dari Asisi dan mengembangkan pemikirannya seputar Allah, alam, dan manusia dalam konteks sosial-politik yang cukup serupa.
Yunus Emre merupakan seorang sufi yang merakyat dan hidup mengembara dalam laku hidup miskin di tanah Anatolia (sekarang Turki), serupa dengan Santo Fransiskus dari Asisi. Sebagai seorang sufi, Yunus Emre tentunya hidup dengan bimbingan guru spiritualnya, yakni Taptuk Emre yang dikenal sebagai salah satu santri kinasih dari Maulana Jalaluddin Rumi yang tersohor dan Haji Bektash Veli yang merupakan pendiri tarikat bektashi di Turki.
Dalam menyebarkan ajaran sufinya, Yunus Emre dikenal sering membuat syair-syair yang sampai sekarang dikenal luas dan dihafal oleh masyarakat Turki secara keseluruhan. Layaknya Santo Fransiskus dari Asisi yang menyampaikan ajaran Katolik dalam bahasa Italia yang sederhana, Yunus Emre menyederhanakan ajaran agama Islam dengan bahasa Turki yang digunakan oleh rakyat sehari-sehari.
Salah satu ajaran Yunus Emre yang menjadi dasar pemikirannya ialah pentingnya untuk memahami dan mengubah diri sendiri sebelum melakukan transformasi terhadap sekitar. Hal itu tergambar dalam bait syairnya: ‘lim ilim bilmekdir, ilim ken- din bilmekdir. Sen kendini bilmezsin ya nice okumakdr yang bermakna: Ilmu itu berarti ilmu untuk memahami kebenaran, dan ilmu untuk memahami kebenaran yang paling paripurna ialah memahami diri sendiri yang menjadi bagian dari ciptaan Tuhan, seberapa besar pun pengetahuan yang dipelajari akan kebenaran, tiada bermakna tanpa pengetahuan akan diri sendiri.
Bait itu disampaikan oleh Yunus Emre sebagai kritik akan para ulama skripturalis yang terlalu berfokus akan kebenaran yang dideliberasi secara tekstual tanpa ada pe- mahaman kontekstual yang baik di alam sekitar. Teologi Islam, menurut Yunus Emre, akan menjadi tidak bermakna tanpa ada refleksi diri yang kuat dan kontekstualisasi kebenaran dalam kehidupan sehari-sehari masyarakat. Pemikiran itu tentunya sejalan pula dengan laku fransiskan yang menekankan pada iman dalam laku, serta iman yang menghidupkan masyarakat dalam tindakan-tindakan yang nyata.
Teologi kasih sebagai sumber laku dan inspirasi dialog
Kesepadanan pemikiran Yunus Emre dan Santo Fransiskus dari Asisi juga terlihat dalam fokusnya akan teologi kasih. Salah satu bait puisi yang menjadi prinsip sentral dalam filsafat Yunus Emre ialah ‘sevelim sevilelim, dunyaya kimseye kalmaz (marilah mencintai dan saling memberikan cinta/ kasih karena tiada sesiapa yang akan hidup selamanya di dunia).
Ketika cinta dan kasih menjadi inti dalam laku agama, ia akan menggerakkan umat beriman untuk berlaku damai dan baik pada sesama. Dalam salah satu ceramahnya, Paus Fransiskus menyampaikan bahwa teologi penuh hikmat kebijaksanaan (sapiential the ology) ialah teologi kasih. Paus Fransiskus menjelaskan pula bahwa siapa pun yang hidup tanpa kasih, ia hidup tanpa Tuhan karena esensi Tuhan ialah kasih.
Sikap kasih mendorong manusia untuk sadar bahwa materialisme dunia bukan merupakan tujuan, melainkn sekadar alat yang membantu manusia untuk melanjut kan hidup di dunia. Sikap berserah diri pada Tuhan-lah yang selayaknya menjadi referensi untuk menyeimbangkan kebutuhan material dan spiritual di dunia yang fana.” Itu tergambar pula dalam bait Yunus Emre, ‘neyi sever isen imann oldur, nice sevmeyesin sultann oldur,(keimanan seseorang itu bergantung apa yang ia kasihi dan apalah arti kasih itu jika tidak dapat memahami kasih sejati yang berasal dari sang Penguasa).
Dalam bait yang lain, Yunus Emre bahkan mengritik sikap rakus dan eksploitatif ma- nusia sebagai salah satu dasar terjadinya konflik yang merugikan sesama manusia dan merusak lingkungan sekitar. Hal itu tergambar dalam bait ‘ana durur buhl u hased key mubariz durur gayet, kokunu kaz yabana at farig otur ey gam- güzar (di mana pun ada sikap kikir dan cemburu, di situlah ada seteru yang menderu. Maka, bersihkanlah jiwamu dan jauhkanlah dirimu dari sikap- sikap seperti itu).
Dalam beberapa kesempatan, Paus Fransiskus juga mengingatkan bahwa sikap materialisme dan hoarding (menumpuk barang) sebagai laku konsumerisme ekstrem yang menjauhkan seseorang dari kebenaran Tuhan, yang menekankan hidup penuh kasih dan hidup yang berbagi pada sesama. Seperti yang tercantum di dalam ensiklik Fratelli Tutti, konflik yang terjadi di dunia merupakan ejawantah dari keserakahan material yang marak terjadi di dunia ini. Sudah selayaknya laku hidup reflektif dan kembara yang dilakukan oleh Yunus Emre dan Santo Fransiskus dari Asisi menjadi inspirasi yang memberikan manusia peluang untuk memotong rantai konflik dengan memahami lingkungan sekitar secara lebih mendalam.
Dengan mendialogkan ajaran fransiskan dan Yunus Emre itu, sudah selayaknya dialog-dialog yang lebih intensif layak dibuka antarumat Islam dan umat Katolik, utamanya dalam isu-isu spiritualisme yang bersifat kontekstual dan menapak tanah. Hal itu amat penting dilakukan untuk mentransformasi agama yang tidak hanya eksis sebagai sekumpulan doktrin, tetapi juga menjadi semangat hidup yang dapat menginspirasi solusi akan masalah-masalah yang mendera masyarakat Indonesia dan dunia.
Tulisan sudah dimuat di rubrik Opini Media Indonesia pada tanggal 13 September 2024
Hadza Min Fadhli Robby
Dosen Jurusan Hubungan Internasional UII. Pengamat politik Turki dan India. Bidang riset pada gagasan politik Islam, studi agama dalam Hubungan Internasional.