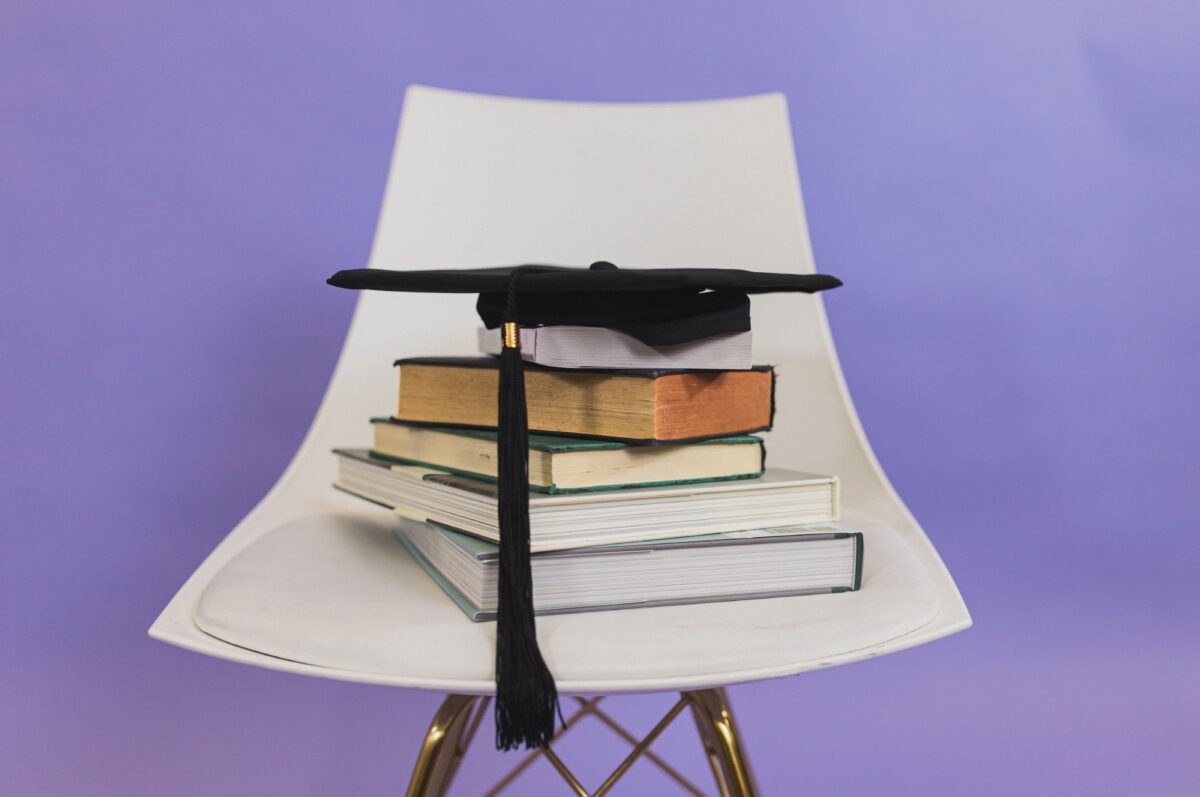Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif di tingkat desa perlu diperkuat. Dengan demikian, BPD dapat menjadi kekuatan penyeimbangan untuk mengawasi pemerintahan desa yang diselenggarakan kepala desa.
Dalam teori dan sistem ketatanegaraan, legislatif memiliki peran yang sangat penting, sama pentingnya dengan kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Secara umum, jamak diketahui legislatif memiliki tiga fungsi utama, yaitu pembuat undang-undang, pengawas pelaksanaan undang-undang, dan penganggaran.
Selain itu, keberadaan legislatif menjadi sangat vital karena merupakan lembaga yang ditengarai mewakili rakyat secara langsung. Oleh karena itu, sejatinya apa yang disuarakan oleh legislatif adalah representasi dari apa yang diinginkan oleh rakyat.
Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan terendah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, keberadaannya setara dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Mereka sejatinya memiliki kedudukan sejajar, yang membedakannya hanyalah cakupan wilayah kekuasaannya.
Bahkan, pemerintahan desalah yang sehari-hari berhadapan langsung dengan masyarakatan dan problem kemasyarakatan. Oleh karena itu, persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan desa jauh lebih kompleks.
Sebagai sistem pemerintahan terendah, pemerintahan desa juga memiliki badan legislatif yang oleh undang-undang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD juga berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa begitu pun menyatakan pendapat atas hasil penyelenggaraan tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, sejatinya BPD sebagai wakil rakyat atau wakil penduduk desa memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, mengawasi pemerintah desa, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dengan kata lain, BPD adalah badan legislatif di tingkat desa.
Sayangnya, keberadaan BPD saat ini masih sangat lemah, baik secara kelembagaan maupun kewenangan. BPD yang sejatinya menjadi mitra pemerintah desa dalam melakukan pengawasan, pengundangan, dan penyalur aspirasi, justru lebih tampak sebagai bawahan dan ”tukang” stempel kepala desa. Dengan demikian, pemerintahan desa sepenuhnya diselenggarakan oleh kepala desa sebagai eksekutif, tidak ada kekuatan penyeimbang untuk melakukan pengawasan. Implikasinya, ada banyak kepala desa atau perangkat desa lainnya yang berurusan dengan aparat penegak hukum, baik karena melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), ataupun penyalahgunaan wewenang lainnya.
BPD yang sejatinya menjadi mitra pemerintah desa dalam melakukan pengawasan, pengundangan, dan penyalur aspirasi, justru lebih tampak sebagai bawahan dan ”tukang ” stempel kepala desa.
Setidaknya ada beberapa logika mengapa legislatif desa, yaitu BPD atau dengan sebutan lain penting untuk diperkuat kelembagaan maupun kewenangannya. Pertama, pepatah lama yang sangat familiar di telinga kita ”power tend to corrupt but absolut power corrupt absolutely” bahwa kekuasaan itu cenderung kepada tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, dan melampaui kewenangan.
Pemerintah desa memiliki prasyarat yang lebih dari cukup untuk melakukan kesewenang-wenangan itu. Dari aspek kewenangan, nyaris tak terbatas karena semua bergantung kepada kepala desa, tidak ada fungsi lain yang menjadi penyeimbang kekuasaan. Dari aspek anggaran, alokasi dana desa dan dana desa memberikan kucuran dana yang cukup besar bagi pemerintah desa, bahkan sangat besar jika dibandingkan sebelum rezim UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Belum lagi ada banyak desa yang memiliki Badan Usaha Milik (BUM) Desa dengan pendapatan di atas rata-rata. Sementara dari aspek masa jabatan, kepala desa menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga periode. Artinya, seseorang dapat menjabat menjadi kepala desa selama 18 tahun. Bahkan, ada pula usulan dari pemerintah pusat untuk menaikkan masa jabatan menjadi sembilan tahun.
Dengan kekuasaan yang sangat besar, mencakup kewenangan, anggaran, dan masa jabatan di atas, adalah niscaya agar pada level desa, memiliki satu badan legislatif yang memiliki kekuatan setara sebagai penyeimbang. Jika tidak, penyalahgunaan wewenang akan terus ada dan semakin masif.
Kedua, dari aspek teoretik, pemerintahan desa juga merupakan wadah pendidikan politik bagi calon kader-kader politik yang akan berkecimpung pada level daerah maupun nasional. Atau dengan kata lain, pemerintahan desa adalah bentuk mini dari pemerintahan daerah ataupun pemerintahan pusat. Oleh karena itu, sistem yang digunakan haruslah sama atau paling tidak mendekati kesamaan.
Pada level pusat dan daerah, legislatif memiliki peran penting sebagai pengawas, pembuat undang-undang dan menyetujui anggaran yang dibuat oleh legislatif. Pada level desa, juga setidaknya memiliki model yang serupa dengan itu, agar desa menjadi laboratorium mini pemerintahan Indonesia yang sebenarnya.
Tulisan sudah dimuat di rubrik Opini Kompas pada tanggal 24 April 2023
Despan Heryansyah
Dosen Fakultas Hukum UII dan Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK). Bidang riset pada hak asasi manusia dan kebijakan publik, hak-hak kelompok rentan, dan pemerintahan daerah.