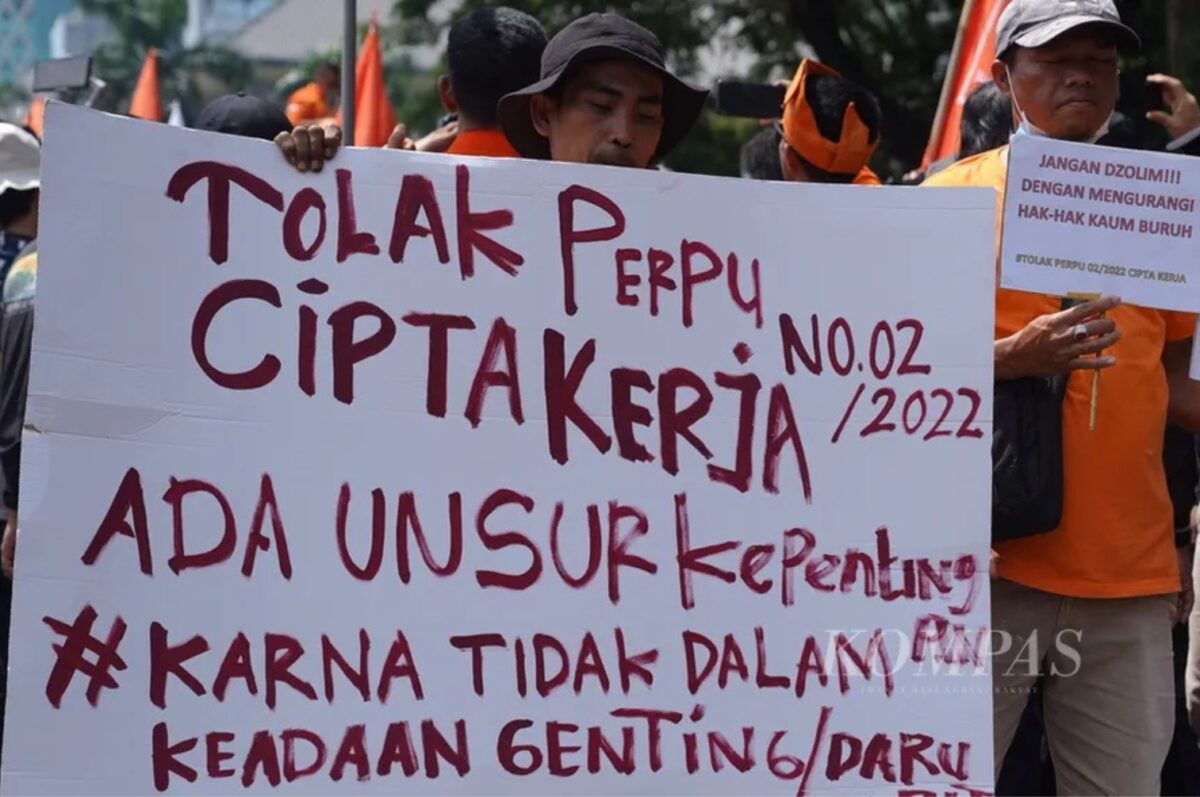Bagaimana membaca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah? Kita memang kecewa dengan hampir seluruh Putusan MK yang terakhir, mengenai syarat usia calon wakil presiden, mengenai sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Tidak hanya kecewa, bahkan publik mengkritik tajam putusan itu, sekaligus mengalamatkan telunjuk jari pada kemandirian dan kapasitas hakim MK.
Namun, semua itu dilakukan tetap dengan kesadaran penuh bahwa Mahkamah Konstitusi adalah the sole interpreter of the constitutionî. Oleh karenanya publik menerima putusan MK sebagai jalan hukum legal yang harus dipilih. Ini adalah prinsip yang kita sepakati bersama saat mendirikan Mahkamah Konstitusi. Di banyak negara, Mahkamah Konstitusi apapun putusannya menjadi akhir dari polemik politik berkepanjangan.
Pada selasa 20 Agustus lalu, Mahkamah Konstitusi menge- luarkan Putusan Nomor 23/P/HUM/2024 dan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, kedua putusan ini mengatur tentang syarat usia calon kepala daerah dan/atau kepala daerah yang sebelumnya berdasarkan keputusan MA 30 tahun terhitung sejak pelantikan, menjadi terhitung 30 tahun sejak penetapan calon sebagaimana Peraturan KPU sebelumnya, serta tentang syarat ambang batas calon kepala daerah dengan syarat calon perseorangan. Sehari pasca putusan MK, DPR melakukan sidang bersama pemerintah dan menyepakati untuk mengenyampingkan putusan MK dan mengikuti putusan MA, serta menolak menerapkan ketentuan ambang batas sebagaimana ditentukan putusan MK.
Melihat animo yang beredar, kalangan akademisi, aktivis, dan jaringan masyarakat sipil, memberi apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi atas Putusan Nomor 23/P/HUM/2024 dan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Tentu saja, jika dibaca lebih jauh apresiasi yang diberikan bukan terhadap instansi Mahkamah Konstitusi atau hakim MK, namun terhadap nilai keadilan dan kebenaran yang diakui bersama terkandung di dalam putusan. Tidak ada yang berubah dari komposisi hakim MK, artinya kita dapat memahami, dalam hegemoni kekuasaan seperti saat ini, mengeluarkan Putusan a quo bukanlah perkara gampang dan mudah, sudah pasti ada tekanan besar baik dari luar maupun dalam MK sendiri.
Kejahatan Konstitusi
Tulisan ini ingin melihat dinamika yang terjadi dari aspek hukum. Pertama, jika dilihat dari kacamata ilmu perundang-undangan, kedudukan Putusan MK, baik Putusan Nomor 23/P/HUM/2- 024 maupun Putusan Nomor 60/PUU- XXII/2024, sangatlah kuat. Memang ada perdebatan di kalangan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara mengenai kedudukan Putusan MK, ada yang mengatakan ia sejajar dengan konstitusi/UUD sehingga berada di atas UUD, ada pula yang mengatakan ia sejajar kedudukannya dengan UU. Terlepas dari perdebatan itu, satu fakta yang diketahui bersama bahwa MK adalah the guardian of the constitution dan the sole interpreter of the constitution, artinya MK lah satu-satunya lembaga yang dapat menafsirkan UUD dengan Putusannya, lalu membatalkan UU, sehingga sekalipun tidak sejajar dengan UUD, namun Putusan MK setingkat lebih tinggi daripada UU, karena merupakan tafsir langsung atas konstitusi. Karena itu, Putusan MK bersifat final dan binding, artinya tidak dapat diuji lagi dan langsung berlaku pada saat itu juga.
Kedua, dengan demikian, maka secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa penolakan terhadap Putusan MK, bukan saja bermakna pembangkangan terhadap putusan itu sendiri, melainkan pembangkangan terhadap konstitusi. Mengapa demikian, karena Putusan MK sejatinya adalah tafsir konstitusi, atau dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa Putusan MK adalah konstitusi yang hidup. Melampaui terminologi itu, penulis lebih setuju menyebut bahwa sejatinya DPR dan Pemerintah telah melakukan kejahatan konstitusi atau kejahatan terhadap konsti- tusi. DPR dan Pemerintah bukan hanya tidak mau menyelenggarakan Putusan MK, namun dengan kesadaran dan mata telan- jang merancang peraturan yang bertentangan dengan Putusan MK, yang mana putusan itu adalah tafsir konstitusi itu sendiri.
Sayangnya, dalam situasi sulit dan darurat seperti saat ini, tidak ada mekanisme bagi rakyat untuk me-recall anggota DPR yang telah dipilihnya. Padahal, logika sederhananya, sebagai pemilih orang yang mewakilinya di parlemen, maka rakyat memiliki hak dan dibuatkan mekanisme, jika suatu ketika merasa keinginan wakil tidak lagi sejalan dengan yang diwakilinya, untuk mencabut kembali mandat yang telah diberikan sebelumnya.
Apa yang dapat dilakukan oleh rakyat hari ini adalah terus mengawal agar Putusan MK sebagai tafsir konstitusi tetap tegak dan dijalankan penyelenggara pemilu, serta terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah tetap berada dalam jangkauan kehendak rakyat.
Tulisan sudah dimuat di rubrik Opini Kedaulatan Rakyat pada tanggal 27 Agustus 2024
Despan Heryansyah
Dosen Fakultas Hukum UII dan Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK). Bidang riset pada hak asasi manusia dan kebijakan publik, hak-hak kelompok rentan, dan pemerintahan daerah.